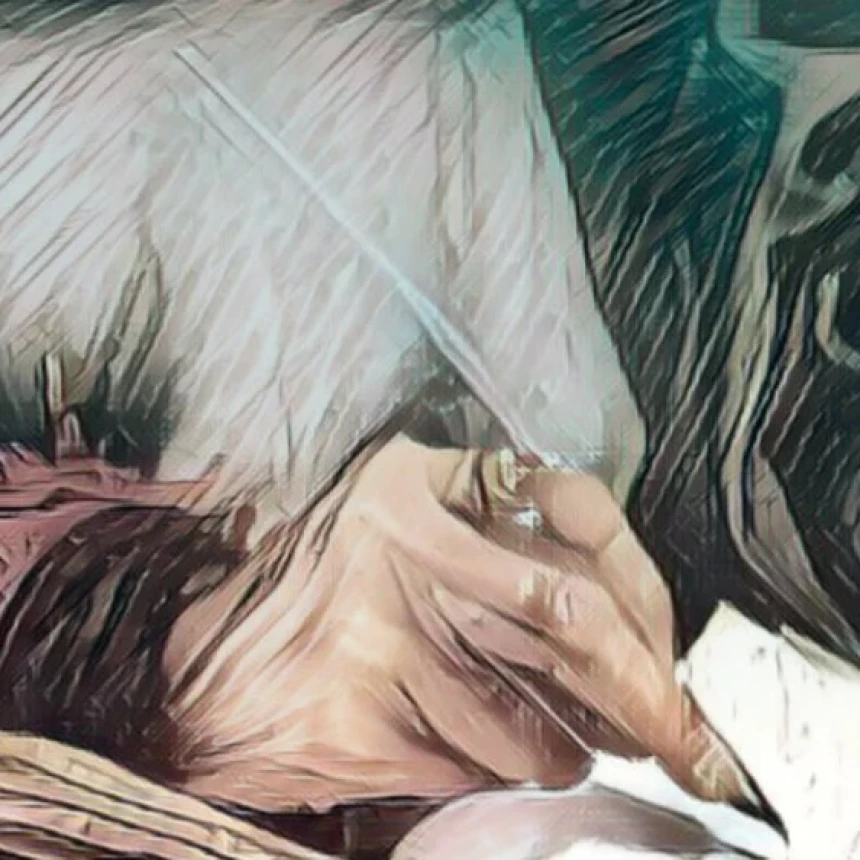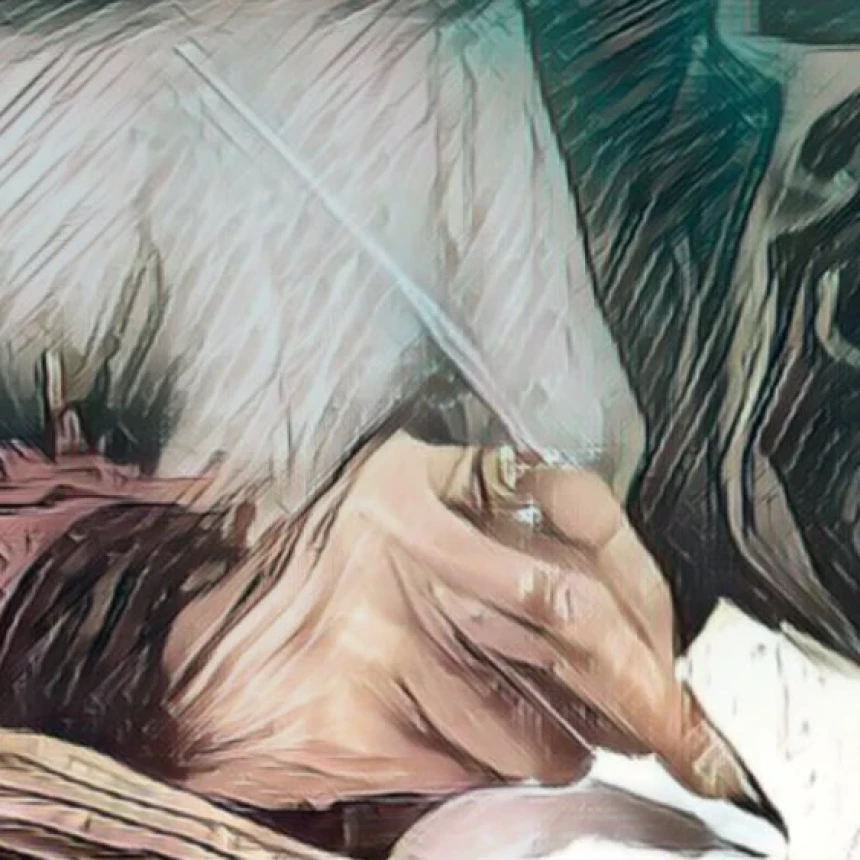Imam Al-Muhasibi: Pelopor Integrasi Syariat dan Tasawuf serta Peletak Etika Ekonomi Islam
NU Online · Rabu, 29 Oktober 2025 | 14:30 WIB
Shofi Mustajibullah
Kolomnis
Nama besar tokoh sufi sekaliber Junaid Al-Baghdadi, merupakan murid dari maha guru para sufi bernama Harits Al-Muhasibi. Ia tidak hanya melahirkan sufi agung sepanjang masa, tetapi menjadi rujukan para ulama pada masa itu. Al-Muhasibi dikatakan sebagai tokoh pertama yang mengintegrasikan antara syariat dan hakikat (tasawuf). Dalam gagasannya, tasawuf tidak sebatas luaran manusia dalam berinteraksi dengan Allah, melainkan masuk ke dalam diri dengan proses introspeksi. Bahkan pada masanya, ia mampu menawarkan konsep rezeki yang lebih manusiawi.
Menarik untuk mendalami gagasan-gagasan sang guru besar para sufi. Namun sebelum itu, sebagai bentuk pengenalan, penulis akan menampilkan latar belakang singkat Al-Muhasibi. Kemudian buah pikirnya yang sangat relevan untuk diimplementasikan.
Latar Belakang Al-Muhasibi
Baghdad merupakan kota yang menghasilkan ratusan hingga ribuan ulama. Salah satunya adalah seorang sufi yang dikenal dengan julukan Al-Muhasibi, bernamakan lengkap Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Seorang yang tekun akan kezuhudan, arif bijaksana, dan menjadi guru besar para sufi (Syamsuddin ad-Dzahabi, Siyar A’lamin Nubala, [Beirut, Muassasah Ar-Risalah: 1983], juz XII, halaman 110).
Al-Muhasibi termasuk seorang ulama interdisipliner. Tidak hanya disiplin ilmu tasawuf yang menonjol pada dirinya, beberapa disiplin ia kuasai, sehingga lahirlah beberapa karya yang sampai saat ini bisa dipelajari.
Ibnu Shalah mengatakan:
Artinya, “Al-Ḥarits mempunyai banyak kitab berkenaan tentang zuhud, pokok-pokok agama, serta bantahan terhadap pihak-pihak yang menyelisihi, seperti kaum Mu‘tazilah, Rāfiḍah (Syiah ekstrem), dan lain-lainnya.” (Thabaqatul Fuqaha’ Asy-Syafi’iyah, [Beirut, Darul Basyair: 1992], juz I, halaman 439).
Selain terkenal sebagai seorang sufi, Al-Muhasibi menonjol pada disiplin ilmu kalam (teologi). Ia mampu beretorika dengan baik dan menarik perhatian lawan debatnya. Pernah satu saat, ia belajar ilmu kalam kepada Abu Muḥammad ‘Abdulluh ibn Sa‘id Al-Qaṭṭan, yang oleh kebanyakan orang dijuluki “Kalab”, dan para pengikutnya disebut Kalabiyyah. Alasan Abu Muhammad dan para pengikutnya, begitu juga Al-Muhasibi, dijuluki kalab dan kalabiyyah dikarenakan kemampuan retorika yang memikat lawan debat, sehingga keterampilan tersebut seakan-akan menarik perhatian para anjing yang tertuju padanya. (Thabaqatul Fuqaha’ Asy-Syafi’iyah, I/440).
Namun karena keterlibatan Al-Muhasibi terhadap ilmu kalam, banyak ulama menentang dan menolak keberadaannya. Kendatipun kualitas keilmuannya sangat luar biasa dalam banyak bidang, akan tetapi karena kondisi saat itu terjadi ketegangan antara mutakallimin (ahli ilmu kalam) dan muhadditsin (ahli ilmu hadits), Al-Muhasibi tidak luput dari celaan dan cercaan (Siyar A’lamin Nubala, XII/111).
Salah satu orang yang paling getol menentang keberadaan Al-Muhasibi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Terdapat riwayat yang mengatakan, Imam Ahmad menganggap Al-Muhasibi sebagai pusat dari segala bencana – yang dimaksud adalah fitnah kalam Jahm (yakni pemikiran Jahmiyyah). Lebih dari itu, karena keterlibatan Al-Muhasibi, Imam Ahmad memperingatkan kepada semua orang untuk tidak mendatanginya, lantaran kebid’ahannya. (Ibnu Abi Ya’la, Thabaqatul Hanabilah, [Kairo, As-Sunnah Al-Muhammadiyah: 1952], juz I, halaman 63).
Baca Juga
Cara Menata Hati menurut Al-Muhasibi
Terlepas dari kontroversi yang menyangkut dirinya, Al-Muhasibi tetap menjadi seorang ulama dengan segudang prestasi yang mengagumkan. Bahkan, ia adalah tokoh pertama yang mengintegrasikan antara ilmu (secara umum/syariat) dengan ilmu hakikat (tasawuf), lalu diikuti empat ulama lainnya, yaitu Al-Junaid, Abu Muhammad, Abul Abbas bin Atha’, Amr Utsman Al-Makki. (Ibnu ‘Imad Al-Hanbali, Syadzaratudz Dzahab, [Beirut, Dar Ibnu Katsir: 1988], halaman 197).
Gagasan Tasawuf Sang Guru Besar
Penyematan gelar Al-Muhasibi pada Abu Abdillah Al-Harits memiliki makna yang mendalam. Menurut As-Sam’ani, Adanya penisbatan Al-Muhasibi dari kebanyakan orang dikarenakan ia selalu mengoreksi diri. Pendapat lain mengatakan ia memiliki kerikil-kerikil yang ia hitung satu per satu ketika sedang berdzikir. (As-Sam’ani, Al-Ansab, [India, Dairatul Ma’arif: 1962], juz XII, halaman 103).
Pertemuan sang murid Al-Junaid dan sang guru Al-Muhasibi, menjadi salah satu kisah masyhur yang menunjukkan bentuk intropeksi diri sang guru. Suatu ketika, sang guru menerima jamuan sederhana sang murid. Tiba-tiba sang guru melepehkan makanannya lalu keluar begitu saja. Beberapa hari kemudian, sang murid bertanya pada sang guru, tentang kejadian sebelumnya.
Sang guru menegaskan, bahwa memang dirinya saat dalam kondisi lapar dan mencoba menyenangkan sang murid dengan menerima jamuannya. Akan tetapi, antara dirinya dengan Allah terdapat tanda, bahwa jamuannya merupakan barang syubhat. Ternyata, makanan yang ditawarkan kepada sang guru adalah pemberian tetangga sang murid dari pesta perkawinan (Al-Qusyairi, Risalah Al-Qusyairiyah, [Kairo, Darul Ma’arif], juz I, halaman 52).
Al-Muhasibi menyusun gagasan sepuluh kriteria agar menjadi seseorang tekun dalam intropeksi diri. Dan ini termasuk gagasan utamanya. Pertama, tidak ceroboh dan selalu bersumpah atas nama Allah. Kedua, menjaga diri dari kebohongan. Ketiga, melanggar sebuah perjanjian. Keempat, meninggalkan kebiasaan melaknat, sekalipun kepada orang zalim. Kelima, tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menyakitimu, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pun demikian dengan berniat membalas dendam kepadanya, tetapi serahkanlah urusannya kepada Allah Ta‘ala.
Keenam, tidak memberikan kesaksian (menilai) bahwa seseorang termasuk dalam kafir, musyrik, atau munafik, karena hal itu menunjukkan kasih sayang dan rasa belas kepada sesama manusia, serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Ta‘ala. Ketujuh, tidak berniat melakukan maksiat, baik secara lahir maupun batin. Kedelapan, tidak membuat orang lain repot atau terganggu, baik dengan hal kecil maupun besar. Kesembilan, tidak bergantung pada orang lain dan hanya bergantung pada Allah. Kesepuluh, tidak memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain, dan orang lain lebih rendah (Fariduddin , Tadzkiratul Auliya’, [Suriah, Darul Maktab:2009], halaman 290).
Pandangannya Terhadap Aktivitas Ekonomi
Dalam kitab Al-Makasib yang sebagian besar menjelaskan tentang etika ekonomi, Al-Muhasibi menantang keras kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa lebih baik menyambung hidup dari pemberian orang-orang berpunya.
Dalih yang dijadikan alasan seperti Allah sudah menjamin rezeki manusia, lantas untuk apa bekerja. Lebih dari itu, kelompok-kelompok yang memilih berpangku tangan menganggap bahwa menunggu pemberian orang lain lebih utama daripada bekerja. Secara tegas, Al-Muhasibi menganggap kelompok-kelompok ini angkuh dan merasa diatas para sahabat, bahkan Qur’an dan Sunnah.
Al-Muhasibi mengatakan:
"Mereka pun menempatkan para tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali – semoga Allah meridai mereka – pada posisi orang-orang lemah dan tak berdaya, sebagai bentuk pengutamaan terhadap diri mereka sendiri, serta keyakinan (yang salah) bahwa pendapat mereka lebih benar, tanpa dasar dari berita yang sah dari Rasulullah ﷺ dan tanpa satu ayat pun dari Kitab Allah Yang Maha Agung.” (Al-Makasib, [Beirut, Darul Fikri: 1992], halaman 44).
Sumber daya dimuka bumi sangatlah terbatas (scarcity), akan tetapi kebutuhan manusia terus bertumbuh. Tindakan atau upaya mendapatkan sumber daya disebut bekerja. Walaupun tetap mengimani adanya rezeki sudah ditetapkan Allah, manusia tetap diwajibkan untuk bekerja. Hasil jerih payahnya kemudian diberikan kepada orang-orang yang ditanggung kehidupannya.
Sekalipun seseorang mencurahkan upaya untuk mendapatkan hasil kerja yang cukup lebih, Al-Muhasibi justru tetap membenarkan. Memang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial akan berambisi mendapatkan hasil yang dicita-citakan untuk ketahanan ekonomi. Dengan syarat tetap mengimani qadha dan qadar. Menurutnya, Allah tidak menuntut untuk menghilangkan watak dasar manusia. ( Al-Makasib, halaman 23).
Setelah membaca secara runut latar belakang, lalu buah pikirnya, penulis berharap pembaca dapat menerapkannya. Bahwa seseorang bisa mengintrospeksi diri dengan beberapa kriteria dan terus melakukan aktivitas ekonomi secara maksimal sekaligus senantiasa mengimani takdir Allah.
Al-Muhasibi meninggal pada tahun 243 H, di tempat ia lahir dan dikenal khalayak luas. Terdapat suatu riwayat, seseorang bernama ja’far hadir saat kematian Al-Muhasibi. Al-Muhasibi berkata, saat ia melihat segala sesuatu yang disukai, ia akan tersenyum. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum, dan seketika itu pula, ia meninggal. Wallahu a’lam.
Ustadz Shofi Mustajibullah, Mahasiswa Pascasarjana UNISMA dan Pengajar Pesantren Ainul Yaqin
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua