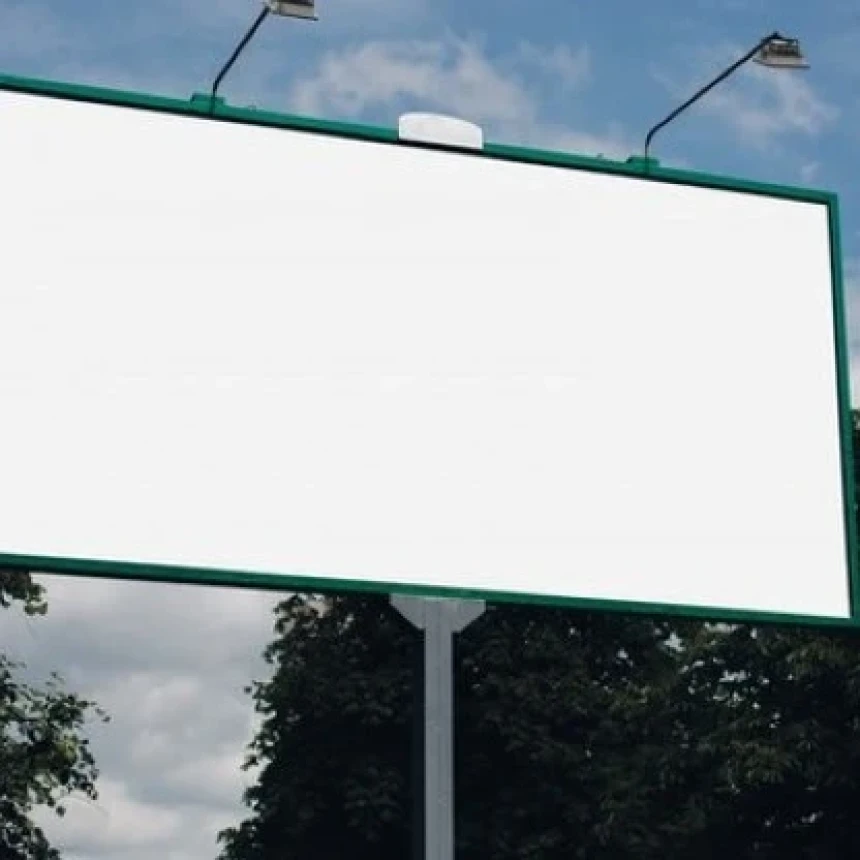Muhammad Daniel Fahmi Rizal
Kolomnis
Zaman berganti. Semakin lama, semakin hilang insan-insan pandai kreasi. Aku salah satunya.
Seumur hidup Aji tidak akan pernah melupakan hari itu. Di tengah terik, dia rela menerjang jalanan ibu kota bersama motor tuanya. Panas dia terabas demi menuju gedung tempatnya bekerja. Biasanya Aji diizinkan bekerja dari mana saja. Akan tetapi, hari itu Aji ada janji bersama pimpinan redaksi. Dan, dia tidak ingin pimpinannya yang menunggu. Dengan bergegas Aji memasuki ruang meeting.
Setelah itu, kisaran satu jam pun berlalu. Aji keluar ruangan dengan langkah lemas. Orang-orang yang berpapasan dengannya, meski beberapa di antaranya dia kenal baik, tidak memberikan senyum ramah seperti biasanya. Entah karena sadar setelah ini tidak ada keperluan lagi dengannya, entah karena takut dengan pimpinan mereka, atau sekadar tidak enak hati karena tahu apa yang baru saja menimpa Aji.
Aji sudah berandai hari ini menjadi hari yang baik untuknya. Awal minggu ini, Aji mendapat undangan rapat dari bagian kepegawaian. Dia membayangkan akan memperoleh kejelasan baru terkait posisinya sekarang. Dua belas tahun sudah dia mengabdi di kantor redaksi Jawa Ekspres. Aji pikir, sudah saatnya dia naik pangkat. Jabatannya tidak lagi ilustrator melulu. Makanya begitu pimpinan redaksi memanggilnya untuk meeting, Aji terbayang yang indah-indah. Dia akan mendapat tambahan tunjangan? Gaji pokoknya naik? Atau malah diminta jadi pimpinan divisi?
Sayangnya kenyataan tidak seindah bayangan. Aji segera merasakan ketidakberesan begitu memasuki ruang rapat. Di dalam sana tidak hanya ada pimpinan redaksi, tapi juga ada pimpinan perusahaan dan staff kepegawaian. Sama sekali tak ada senyum merekah di wajah mereka. Rasa gundah Aji terjawab. Kata pimpinan, kontrak kerja Aji tidak bisa diteruskan.
“Kamu tahu, Ji. Beberapa tahun ini oplah koran terus menurun,” dalih pimpinan perusahaan.
Dalam hati Aji bersungut. Siapa seharusnya yang harus mikirin oplah. Itu urusan bagian perusahaan. Aji cuma ilustrator. Tugasnya bikin visual agar koran enak dipandang.
“Pembaca koran makin menyusut. Coba kau pikir, siapa sekarang yang baca koran? Hanya orang-orang tua yang tidak akrab dengan gawai. Dan itu angkanya sangat kecil, Ji.”
Hati Aji masih dikepung emosi. Pikirnya, itu tugas pimpinan dong buat cari pembaca baru!
“Kita beruntung masih sanggup hidup. Tapi, operasional tidak bisa terus begini. Penyesuaian harus dilakukan. Makanya kami harus mengurangi staff, Ji. Mohon dimengerti.”
Halah, penyesuaian. Caranya pakai diksi sudah mirip politisi. Bilang saja perlu memecat karyawan biar enggak rugi!
“Kami sangat menghargai pengabdianmu, Ji. Dua belas tahun bukan waktu yang singkat,” lanjut si pimpinan masih berusaha mencari pemakluman.
Tentu saja! Dua belas tahun bekerja demi perusahaan ini. Dari bikin gambar manual sampai pakai cara digital, semua dicoba agar koran ini tidak ketinggalan zaman.
“Kami tidak akan lepas tanggung jawab. Pesangon akan tetap kamu peroleh. Kami ingin kerja sama denganmu berakhir baik-baik.”
Sisa obrolan selanjutnya tak bisa dicerna Aji dengan baik. Kekalutan mengitari kepalanya. Seusai keluar dari ruang meeting, Aji tak tahu ke mana nasib akan menggiringnya. Hidupnya selama dua belas tahun ini hanya menggambar dan menggambar. Jika rumah tempatnya menggambar tidak menerima dia lagi, ke mana lagi dia bisa menukar karya-karyanya dengan pundi rupiah?
***
Semenjak kejadian itu, hidup Aji seakan kehilangan gairah. Aji tidak berminat melakukan apa-apa. Hari-hari dia jalani dengan gegoleran sambil scroll video pendek di gawai. Bosan menonton video, ganti dia membaca manga di situs baca ilegal. Kalau matanya sudah lelah, ganti dia beranjak tidur. Itu-itu saja yang dia lakukan, dari subuh sampai hari berganti malam. Dalam hati Aji berusaha memaklumi. Dia sedang kecewa. Dia merasa punya hak untuk tidak ngapa-ngapain.
Terus menerus memaklumi, tak terasa satu minggu telah terlewati. Aji masih saja malas keluar kost-an. Segala macam aktivitas yang berhubungan dengan isi perut dia lakukan secara daring. Belanja kebutuhan pokok juga sama. Aji cuma keluar kamar kalau mandi dan memasak kopi. Maklum, kost-nya murah. Kamar mandi dan dapur letaknya terpisah.
Sampai di suatu siang, Aji terpaksa meninggalkan kasur tercintanya. Hari itu Aji dapat notifikasi barang pesanannya sudah selesai diantar kurir. Aji lupa kalau sehari sebelum dipecat dia pesan action figure karakter anime favorit dia. Dulu saat pemasukannya tetap, menyisihkan gaji untuk koleksi adalah kewajaran. Kini tatkala menjadi pengangguran, beli-beli sesuatu seolah menjadi hal tabu.
Aji tak tahu kalau nasibnya berubah di waktu semingguan ini. Barang sudah dibeli, mau tak mau harus diterima. Dengan gontai Aji berjalan menuju ruang tamu kost-an, tempat segala macam paket ditaruh induk semang.
Sesaat setelah mengambil paket pesanannya, mata Aji tiba-tiba tertuju di meja ruang tamu. Ada koran Java Ekspres edisi hari ini! Rasa penasaran tiba-tiba menyeruak. Bagaimana pemandangan rubrik-rubrik yang biasa diisi ilustrasi oleh Aji? Siapa ilustrator pengganti dirinya?
Hati Aji masih terasa sesak gara-gara dipecat. Ada sedikit rasa takut saat dia melihat Java Ekspres. Rasanya masih sulit dia menengok koran itu. Namun ternyata, setakut-takutnya dia, perasaan kepo terlalu dominan di dalam hati. Perlahan dia memutuskan untuk memungut koran tersebut. Pelan-pelan, dengan dada berdebar, dia buka halaman demi halaman.
Mata Aji membelalak saat dia melihat rubrik yang biasa dia isi. Di situ memang ada gambar. Tapi tidak ada nama ilustrator tercantum.
“JINGAN! PAKE AI!”
Pisuhan meluncur deras dari mulut Aji. Betapa rasa takut dan penasaran tadi seketika berubah menjadi rasa marah. Java Ekspres memecat ilustratornya hanya untuk diganti dengan… artificial intelligent alias kecerdasan buatan?!
***
“Ini bukan pemecatan, Zen! Ini pengkhianatan!”
Malam hari itu juga, Aji memutuskan bertemu Zen, teman kuliahnya yang kini berprofesi sebagai desainer grafis. Begitu Aji melihat gambar AI di Java Ekspres, rasa malasnya untuk bersosialisasi mendadak sirna. Dia ingin marah. Dan, siapa lagi yang bisa jadi tempat sampah Aji selain Zen.
“Bolehlah mereka memecatku kalau ingin mencari pekerja baru. Paling tidak mereka bisa cari fresh graduate minim pengalaman yang mau dibayar murah. Tapi mengganti ilustrator yang sudah belasan tahun kerja bareng mereka pakai AI, logikaku benar-benar tak bisa menerima itu!” Aji menumpahkan kemarahannya di depan Zen.
Zen menyeruput seduhan kopi sachet di depannya. Dia kenal betul kawannya yang kadang suka meledak itu. Makanya, dia biarkan Aji mengeluarkan seluruh kekesalannya.
“Aku bukannya tidak setuju dengan perkembangan zaman ya, Zen. Oke lah, teknologi semakin canggih. Tapi bikin gambar pakai AI itu kan masih problematis.”
“Iya, iya. Aku tahu,” Zen perlahan menanggapi.
“Coba kau pikir! Apa yang punya teknologi AI itu izin sama yang punya gambar? Kamu pikir perusahaan AI itu izin ke Pixar pas bikin gambar mirip style-nya Studio Pixar? Mereka itu dicolong data-datanya, Zen!”
“Dan sekarang yang pakai generate AI itu pers. Kantorku, yang katanya menjunjung tinggi integritas dalam bekerja, rela memecat karyawannya buat diganti pakai gambar colongan!”
Menit demi menit berlalu dengan Aji yang tak henti meracau dan Zen yang khidmat mendengarkan. Zen sadar, di momen seperti ini bukan saatnya dia banyak menanggapi. Aji cuma ingin didengar. Menunggu emosi Aji mereda, barulah Zen perlahan mulai berbicara.
“Ya, begitulah, Ji. Aku paham kamu pasti marah. Tapi, kita bisa apa? Protes ke Java Ekspres? Bikin gaduh sampai viral? Iya kalau netizen bela kamu,” ujar Zen.
Yang diajak omong menghela napas. Perlahan Aji mulai mencerna.
“Kau tahu kan, mau sebagaimana pun idealisnya kita, orang-orang pasti lebih tertarik pakai cara instan. Jangan sampai kamu bikin pembelaan tapi malah dirundung sama orang-orang,” lanjut Zen.
“Iya, sih,” Aji menjawab lirih. Sejenak dia jadi bisa menerima fakta.
“Mending sekarang kamu mikirin besok ganti kerja apa. Jangan lama-lama nganggur-nya. Kelamaan nganggur itu enggak enak,” kata Zen.
“Ya sudah. Kamu ada lowongan kerjaan enggak?”
***
Waktu pun berlalu. Sembilan bulan sudah Aji tidak memiliki pekerjaan tetap. Selepas pertemuan dengan Zen, Aji telah menjajal beragam pekerjaan. Pernah dia jadi desainer lepas, yang kemudian dirasa tidak cocok karena basis Aji adalah ilustrasi. Pernah juga dia mencoba menjual ilustrasi di platform luar negeri. Tapi karena persaingan harga yang brutal, dia memutuskan untuk berhenti.
Sampai tibalah di hari itu, hari ke-21 bulan puasa. Lebaran tinggal sebentar. Aji harus pulang ke kampung halaman. Di sana menunggu para ponakan yang jumlahnya sampai belasan. Sebagai bungsu, Aji sudah menerima kenyataan kalau dia harus berbaik hati pada anak-anak kakak-kakaknya. Ini lantaran selama kuliah jurusan seni, kakak-kakaknya lah yang iuran membiayai studi Aji.
Atas dasar kenyataan tadi, Aji mau-mau saja menerima tawaran pekerjaan kali ini. Pekerjaannya menjadi juri lomba gambar tingkat SMP. Meski hanya lomba gambar dengan peserta murid SMP, tapi penyelenggaranya lembaga negara. Tentu saja, honornya begitu menggoda. Nah, yang bikin beda, lomba gambar kali ini bukan sembarang lomba gambar. Para peserta lomba bersaing menghasilkan gambar lewat ketikan “arahan”.
“Arahan” alias prompt. Seutas kalimat yang ditulis di mesin kecerdasan buatan untuk kemudian dibuatkan hasil gambarnya. Betul sekali, Aji menjadi juri lomba gambar AI.
Negara sedang tidak baik. Ekonomi sedang tiarap. Banyak yang jadi pengangguran mendadak. Daya beli menurun, yang punya usaha sudah pasti terdampak. Ini terjadi gara-gara kebijakan pemerintah yang amburadul. Pimpinan negara atraksi semaunya. Wakil rakyat kongkalikong dengan penguasa. Sementara, aparat pingin dapat ceperan dari luar tupoksinya. Rakyat yang berteriak didiamkan saja. Bahkan, diadu antarsesamanya.
Sengkarut negara ditambah tuntunan menjelang hari raya menggoncang prinsip yang Aji miliki. Aji yang sekarang berbeda dengan Aji yang marah-marah sembilan bulan lalu. Aji yang sekarang bakal menerima pekerjaan apa saja. Yang penting rekening aman dan bisa berbagi saat lebaran.
Buat pekerjaan kali ini, Aji malas ambil pusing. Pokoknya kerjaan beras, dapat uang, pulang. Aji tidak peduli dengan keadaan peserta yang tidak menguasai fundamental gambar. Dia juga ikut saja segala arahan panitia lomba. Pun saat meresmikan pembukaan acara. Aji diminta menempelkan tangannya ke layar televisi. Begitu tangan menempel, layar menunjukkan hitung mundur. Selepas angka nol, lomba resmi dimulai. Canggih nian. Padahal televisinya bukan model yang touchscreen.
Tak butuh waktu lama buat Aji memilih gambar terbaik. Bagaimana mau lama, wong style gambarnya sama semua. Aji serahkan gambar pilihannya ke panitia. Yang tak dia sangka, ketua panitia tiba-tiba mendekat sambil berbisik kepadanya.
“Mas Aji, gambar yang menang dari peserta nomor tujuh saja,” ujar ketua panitia dengan lirih.
“Lha, kok?” Aji menjawab dengan tanya.
“Anu, yang nomor tujuh itu masih keponakan ‘bapak’, Mas Aji.”
Begitu mendengar kata “bapak”, Aji langsung paham siapa yang dimaksud. Aji maklum saja. Lomba ini diinisiasi lembaga negara. Mau tidak mau pasti ada “bapak” yang keinginannya menjadi titah bagi para aparatur sipil.
Aji menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia jadi kepikiran. Si ketua panitia ini jadi mirip AI: mengerjakan apa yang diperintahkan. Bedanya, AI tidak dikaruniai nurani. Etis ataupun tidak, AI tidak peduli.
“Ya sudah, lah. Terserah saja. Saya manut.”
Rangkaian acara berlanjut. Pemenang diumumkan. Penyerahan hadiah dilakukan. Semuanya serba gegap gempita. Meski demikian, bagi Aji semuanya terasa begitu artifisial; sangat dibuat-buat. Aji mulai muak. Begitu amplop berisi honor mendarat di tangan, dia segera bergegas pulang.
Di atas motor tuanya, Aji tertawa sinis. Bikin gambar pakai AI saja sudah curang. Lha yang tadi, begitu dilombakan, masih saja dicurangi panitianya. Curangnya kuadrat. Aji jadi kepikiran, ternyata secanggih-canggihnya kecerdasan buatan, masih kalah dengan kejahatan alami. Tidak peduli teknologinya secanggih apa, kalau manusianya yang rusak, tetap saja dunianya ikut rusak.
Terpopuler
1
Begini Tata Cara Pelaksanaan Shalat Idul Fitri
2
3 Amalan Sunnah Sebelum Berangkat Shalat Idul Fitri
3
Sejumlah Negara Rayakan Idul Fitri 1446 H pada Ahad, 30 Maret 2025
4
4 Amalan yang Dianjurkan pada Malam Idul Fitri
5
Niat dan Waktu Mandi Sunnah Idul Fitri
6
Lafal Bilal Shalat Idul Fitri, Dilengkapi Latin dan Terjemah
Terkini
Lihat Semua