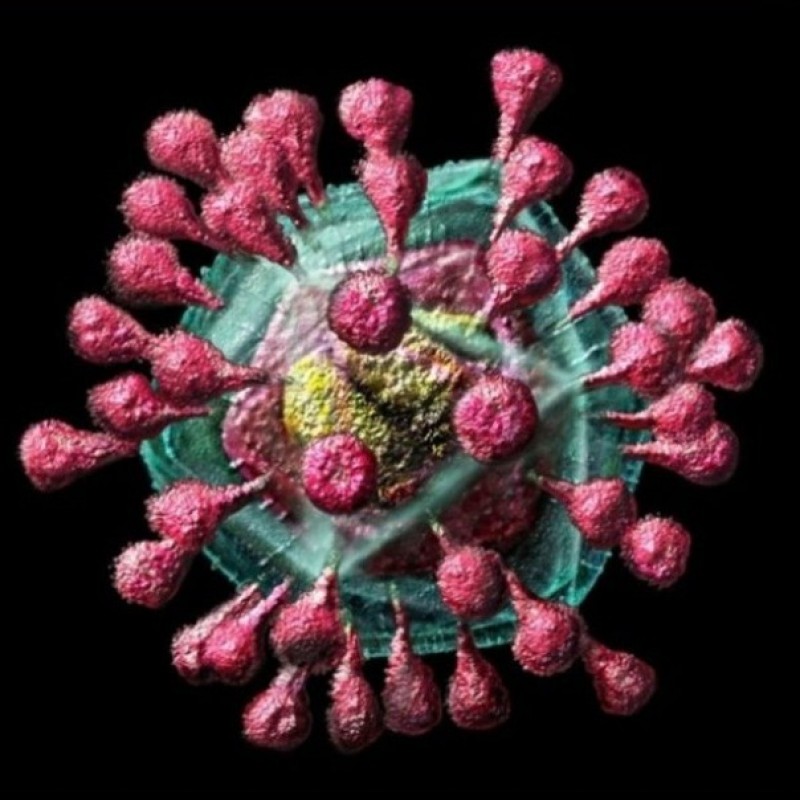132 Tahun KH Abdul Wahab Chasbullah (2): Formasi Tua-Muda
NU Online · Rabu, 1 April 2020 | 06:00 WIB
Sebagai organisasi yang baru berdiri, Kiai Wahab Chasbullah mendesain NU dengan tua muda seiring sejalan. Untuk itu, menurut Kiai Saifuddin Zuhri pada buku Almaghfurlah KH Wahab Chasbullah Bapak Pendiri NU, Kiai Wahab meletakkannya melalui formasi syuriyah-tanfidziyah.
Baca: 132 Tahun KH Abdul Wahab Chasbullah (1): Motor Harley Davidson
Syuriyah dipuncaki Hadratussyekh hingga wafatnya dengan gelar raisul akbar, mahaguru umat Islam waktu itu, sementara tanfidziyah digawangi Hasan Gipo, seorang yang lebih dikenal sebagai saudagar. Sementara arsitektur operasional organisasi dijalankan kepada Mas Sgeng Yudadiwirya, sekretaris presiden HBNO.
Tak heran kemudian di statuten pertama NU, menyebutkan bahwa organisasi ini digerakkan oleh ulama dan bukan ulama. Istilah ini, secara bahasa, memang agak aneh jika dilihat dari sudut sekarang. Namun, maksudnya semuanya, baik tua maupun muda, profesi dan keahliannya apa pun harus bekerja sama untuk sama-sama membangun organisasi yang membela kalangan bermazhab empat.
Muda dalam arti usia, Kiai Wahab sudah mempersiapkannya jauh hari, melalui lembaga bentukannya, Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar. Pada awalnya keduanya merupakan kelompok diskusi, tapi kemudian menjadi lembaga pendidikan yang didukung seorang donatur KH Dahlan Abdul Qohar. Bahkan dia menjadi direkurnya.
Muda dalam arti usia, Kiai Wahab melibatkan Tohir Bakry dan Abdullah Ubayd. Kemudian Mahfuudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, Abdul Wahid hasyim, Muhammad Dahlan, Masykur, dll dalam mengelola NU. Mereka jadi tulang punggung NU hingga akhir hayatnya. Tak berbelok sedikit pun di segala musim.
Mahfudz Shiddiq di kemudian hari, saat menjadi redaktur Berita Nahdlatoel Oelama, menafsirkan syuriyah dan tanfidziyah ala Kiai Wahab. Menurut dia, dalam kinerja, syuriyah tidak boleh menghalangi tanfidziyah, sementara tanfidziyah tidak memadarati syuriyah. Lagi-lagi keseiringan. Bukan belah-membelah.
Meski demikian, seorang rais aam syuriyah punya hak veto. Sebab kedudukan itu merupakan pemimpin tertinggi di NU, meski tentu saja setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Konon, Kiai Wahab pernah melakukannya saat ia mengemban kedudukan itu sejak 1947 sampai 1971. Namun, saya belum bisa menunjukkannya. Karena itulah, menurut Kiai Saifuddin Zuhri, dalam kasak-kusuk Kiai Wahab pernah dijuluki tukang veto, tapi di kalangan NU ia lebih dihormati sebagai "bintang muktamar", dan "jago tua kita".
Sebagai bintang muktamar, Kiai Wahab merupakan orang yang tak pernah absen sekalipun saat hajatan akbar itu digelar NU. Di Jawa maupun di tempat-tempat terjauh. Kecuali setelah ia tak bisa sama sekali untuk pergi karena tutup usia pada tahun Desember 1971.
Di dalam arena muktamar, Kiai Wahab selalu tekun mengikuti perkembangan dan mencari jalan keluar jika ada persoalan yang dihadapi organisasi. Misalnya, saat muktamar NU keenam di Cirebon, panitia muktamar sulit mendapatkan izin pemerintah. Karena kepiawaaiannya dalam berdiplomasi, kesulitan teratasi.
Begitu pula ketika Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari ditangkap kemudian dipenjara Jepang. Kiai Wahab bersama Kiai Wahid Hasyim menjalankan segala cara sampai akhirnya Hadratussyekh dibebaskan. Bahkan kemudian ditetapkan sebagai shumubu. Ya, Kiai Wahab dikenal sebagai seorang pokrol bambu juga waktu itu. Artinya, ia yang bukan lulusan sekolah hukum menjadi pembela seseorang yang terjebak di pengadilan. Tak hanya kepada ia bela, melainkan masyarakat biasa juga.
Jago tua kita adalah julukan dari Berita Nahdlatoel Oelama untuknya. Julukan ini ada hubungannya dengan julukan sebalumnya, yakni kemampuan berdiplomasi dengan siapa pun, termasuk berdebat. Dan Kiai Wahab tentu paham bagaimana menjalankannya.
Misalnya, pada masa awal berdiri NU, undangan menghadiri muktamar dikirimkan kepada para kiai di Cirebon. Namun, sampai muktamar keempat, hanya seorang yang hadir. Padahal, mestinya Cirebon lebih semarak dengan kehadiran banyak kiai mengingat banyak santri lulusan Tebuireng. Dalam penelusuran Swara Nahdlatoel Oelama, pasalnya di Cirebon waktu itu ada seorang ulama yang disepuhkan yang kurang sepakat dengan organisasi. Menurut sesepuh itu, dalam Islam tak ada berjamaah kecuali dalam shalat, mengaji dan jihad.
Kiai Wahab akhirnya turun tangan dengan menerbitkan sebuah tulisan bahwa apa yang dimaksud sesepuh Cirebon itu adalah bagian dari kerja-kerja NU. Soal mengaji misalnya, di NU ada bahtsul masail. Itu adalah berjamaah mengaji. Soal jihad, menurut Kiai Wahab, memperjuangkan Ahlussunah wal Jamaah merupakan bagian dari itu.
Begitulah, kemudian pada muktamar kelima di Pekalongan, 15 ulama Cirebon hadir. Tahun berikutnya, Cirebon sendiri menjadi tuan rumah, hajatan akbar yang waktu itu digelar setahun sekali.
Penulis: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua