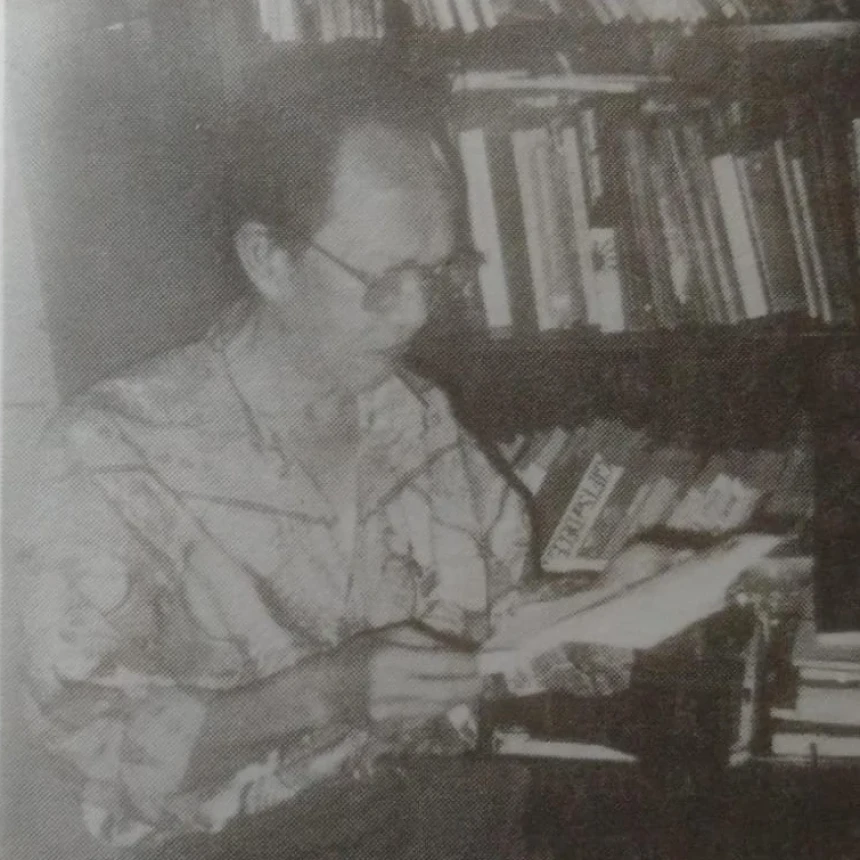Mengenang Mahbub Djunaidi: Dari Kasur Empuk dan Panggung Politik NU
NU Online · Ahad, 5 Oktober 2025 | 15:37 WIB
Sofian Junaidi Anom
Kolomnis
Sebagai anak yang lahir dari bapak dan ibu aktivis Nahdlatul Ulama (NU), mengenal dan mengidolakan tokoh NU sudah menjadi tradisi dalam keluarga saya. Selain para tokoh pendiri NU, tentu saja nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur termasuk yang paling sering disebut. Namun, nama Gus Dur mulai saya kenal ketika masa kanak-kanak dan beranjak remaja. Jauh sebelumnya, ada nama lain yang bahkan sudah saya kenal sejak balita. Nama itu adalah Mahbub Djunaidi, tokoh NU yang pada bulan Oktober ini tepat 30 tahun kepergiannya.
Menempatkan Gus Dur dan Mahbub Djunaidi dalam satu bingkai perbincangan merupakan hal yang lumrah sekaligus menarik, meski keduanya menempati panggung ketokohan yang berbeda. Mahbub adalah seorang maestro di medan jurnalistik dan aktivisme politik. Sementara itu, spektrum Gus Dur melintas batas lebih luas, mencakup perannya sebagai budayawan, kiai, tokoh kemanusiaan, pemikir, hingga puncaknya sebagai Ketua Umum PBNU selama tiga periode dan Presiden Republik Indonesia.
Perbedaan itu tercermin pula dalam corak kepenulisan mereka. Memang, keduanya sama-sama penulis kolom yang produktif dan kerap menjadikan humor sebagai senjata. Namun Gus Dur juga meninggalkan warisan tulisan ilmiah berbasis riset. Sebagai sesama pemikir kritis, mereka tak jarang berseberangan pandangan, sebuah tradisi dialektika yang memperkaya khazanah pemikiran di tubuh NU.
Dialektika intelektual mereka adalah contoh paling gamblang dari adagium lawas yang pernah saya ulas melalui tulisan berjudul “Masa Depan Komunikasi Internal NU di Era Digital”, yang berbunyi, “NU itu kalau rapat lewat koran.” Perdebatan di antara mereka sesungguhnya merupakan representasi publik dari pertarungan dua faksi besar NU kala itu. Kubu Situbondo, dimotori Gus Dur bersama para kiai sepuh, mendorong NU kembali ke Khittah. Sementara Kubu Cipete, tempat para politisi senior seperti Mahbub Djunaidi berada, meyakini perjuangan NU harus tetap melalui jalur politik praktis. Sebagai salah satu motor penggerak dialektika tersebut, sosok Mahbub Djunaidi terasa begitu intim dan personal bagi saya. Namun, kedekatan ini terjalin bukan hanya karena kekaguman intelektual, melainkan juga melalui jalinan cerita keluarga yang hangat.
Ikatan emosional itu berbentuk sebuah kenangan yang sering diulang almarhum bapak saya. Sebagai sesama aktivis yang pernah ditempa di PMII, kekaguman bapak pada Mahbub Djunaidi, Ketua Umum pertama PMII, sudah terbangun sejak lama. Kiprah sebagai kader NU dan PPP pada era 70-an mengantarkan beliau terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pemilu 1977. Amanah legislatif itu masih diembannya untuk beberapa periode berikutnya.
Di tengah masa perjuangannya itulah, bapak berkesempatan menumpang menginap di kediaman Mahbub Djunaidi saat mengikuti sebuah kegiatan di Jakarta. Dalam ceritanya kepada ibu, yang turut saya dengarkan ketika masih kecil, kesan yang paling melekat justru sebuah hal sederhana. Untuk pertama kalinya, bapak merasakan tidur di atas kasur yang begitu empuk—jauh berbeda dari kasur kapuk di rumah. Pengalaman merasakan keramahan sang idola secara langsung inilah yang memantapkan hati bapak untuk mengabadikan kekaguman dengan meminjam nama “Djunaidi,” yang sebetulnya merupakan nama ayah Mahbub, untuk disematkan pada nama tengah saya.
Kekaguman bapak tidak hanya berhenti pada cerita di ruang keluarga. Ia juga membawanya, dan saya, ke arena publik. Saya masih ingat dengan jelas, pada sebuah kampanye akbar PPP di Mojosari, Mojokerto, tahun 1982, bapak mengajak saya yang masih ingusan untuk menemani Mahbub Djunaidi yang hadir sebagai juru kampanye nasional. Malam itu, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok di balik nama yang saya sandang memukau ribuan massa dengan orasi yang berapi-api namun tetap jenaka.
Maka, melampaui sekadar kenangan personal, sosok Mahbub Djunaidi mewariskan sebuah tantangan intelektual, yakni untuk terus menggali dan mengenalkan kembali relevansi pemikirannya di tengah zaman yang berubah. Di momentum 30 tahun haulnya ini, marilah kita menengok kembali berbagai dimensi ketokohan sang pendekar pena, mulai dari satirnya yang tajam, novelnya yang menggugah, hingga perannya sebagai organisatoris ulung yang menjadi salah satu garda terdepan perjuangan NU.
Baca Juga
Ketika Mahbub Djunaidi Membela Subhan ZE
Julukan “Pendekar Pena” bukanlah kiasan kosong; itulah identitas hakikinya. Di dunia jurnalistik nasional, namanya disegani karena ketajaman analisis yang dibungkus dalam gaya khas. Ia adalah maestro satire. Tulisannya kritis, sering menohok jantung kekuas-aan, namun tidak pernah jatuh pada sinisme. Senjatanya adalah humor cerdas dan perumpamaan tak terduga yang membuat pembaca tersenyum lebih dulu sebelum merenungkan kritik pedas di baliknya. Kepiawaian ini paripurna tersaji dalam kolom legendaris “Asal-Usul” di harian Kompas, tempat ia membuktikan bahwa untuk menjadi kritis, seseorang tidak harus kehilangan keceriaan.
Namun, membatasi Mahbub hanya sebagai “Pendekar Pena” berarti mengabaikan dimensi lain dari kepiawaiannya sebagai seorang sastrawan. Melalui novel seperti “Dari Hari ke Hari”, ia merekam denyut zaman dan kegelisahan manusia Indonesia. Lebih dari itu, Mahbub adalah jembatan intelektual. Ia membuka jendela dunia bagi pembaca di Indonesia melalui karya-karya terjemahan yang monumental. Menerjemahkan Animal Farm karya George Orwell menjadi Binatangisme bukan sekadar alih bahasa, melainkan tindakan intelektual yang menghadirkan kritik atas totalitarianisme kepada publik yang lebih luas.
Pemikiran Mahbub Djunaidi juga tidak berhenti di atas kertas. Ia adalah organisatoris ulung, seorang eksekutor gagasan yang percaya pada pentingnya institusi. Peran sentralnya dalam mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan jabatan sebagai Ketua Umum pertama adalah bukti sahih kemampuannya meletakkan fondasi kaderisasi bagi generasi muda Nahdliyin. Dari sana, ladang pengabdiannya meluas ke ranah politik praktis. Bagi Mahbub, politik bukanlah tujuan, melainkan alat perjuangan. Ia percaya aspirasi warga Nahdliyin harus diperjuangkan dari dalam sistem, sebuah sikap ideologis yang merepresentasikan pandangan “Kubu Cipete” pada masanya.
Tiga puluh tahun setelah kepergian Mahbub, warisannya terasa semakin relevan. Ia tidak hanya mewariskan ribuan tulisan, tetapi juga sebuah cara berpikir, cara berdebat, dan cara berjuang dengan akal sehat dan humor. Ia menunjukkan bahwa kritik paling tajam bisa disampaikan dengan cara paling elegan, dan perbedaan pendapat, bahkan dengan sahabat seperjuangan sekaliber Gus Dur, adalah vitamin, bukan racun, bagi kedewasaan organisasi dan bangsa.
Di tengah zaman yang kerap gaduh oleh caci maki, mengenang Mahbub Djunaidi berarti merindukan kembali nalar jernih yang dibalut keceriaan. Sebuah warisan pemikiran yang, rasanya, akan selalu kita butuhkan.
Sofian Junaidi Anom, Pengurus LTN PBNU dan penggerak Komunitas Terong Gosong yang juga pernah aktif di PMII.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
4
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua