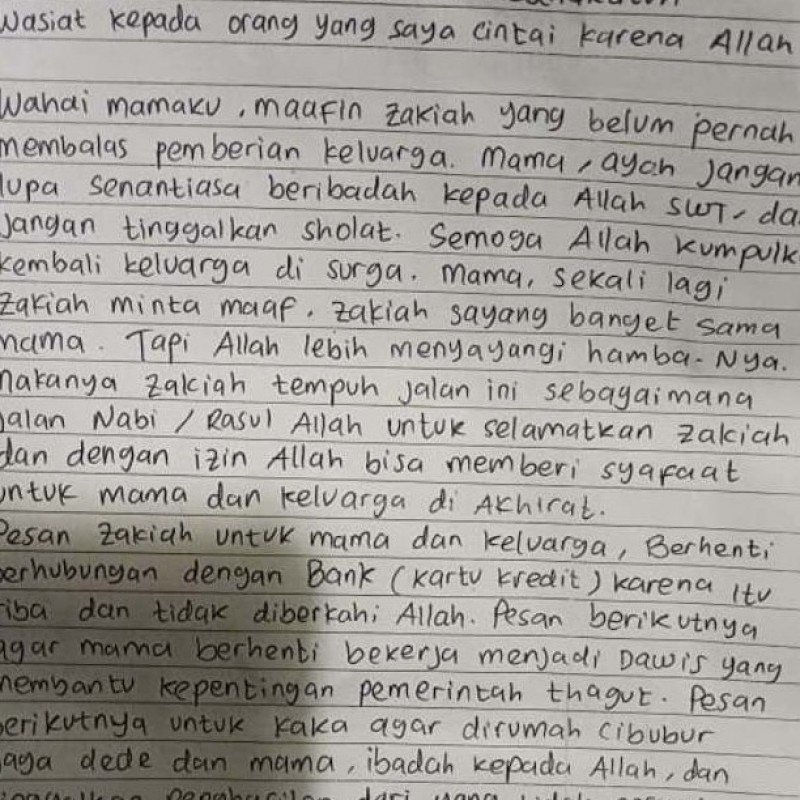Achmad Murtafi Haris
Kolomnis
Mustafa Mahmud, penulis kuat Mesir, pada 1996 menerbitkan kumpulan tulisan opininya dan memberinya judul “Di Ambang Bunuh Diri” (Arab: ‘Ala Hafat al-Intihar). Dia mengomentari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok Islam terhadap Israel dan menyebutnya sebagai perlawanan atas yang mustahil. Dan menganggapnya sebagai aksi fida’ atau martir atau jibakutai bukan aksi terorisme. Kata “mustahil” menjadi kata kunci di sini. Yaitu bahwa bom bunuh diri adalah wujud dari ketidakmampuan melawan secara konvensional sehingga menempuh cara bunuh diri.
Dalam kasus Palestina, Israel begitu digdaya. Dia berhasil menguasai wilayah Palestina dan menjadikan 4 juta warga Arab terusir. Cengkeraman semakin kuat dengan kepemilikan senjata nuklir yang menjadikannya mustahil dikalahkan dan berada di atas angin. Frustasi oleh kenyataan itu, pejuang Palestina menempuh jalan non-konvensional dan darah pelaku pun tumpah.
Dalam perlawanan atas penjajah, angkat senjata bahkan bom bunuh diri tidak pernah disebut terorisme. Ia bagian dari perlawanan bersenjata. Tanpa meremehkan mahalnya darah pelaku dan korban, kata Mustafa Mahmud, bom bunuh diri di Palestina banyak yang memakluminya dan menganggap pelakunya sebagai martir. Hal ini lantaran kepastian posisi penindas dan tertindas, posisi penjajah dan terjajah. Posisi awal ada di Israel dan kedua ada di Palestina.
Sekarang bagaimana dengan bom bunuh diri negara-negara mayoritas Muslim seperti di Pakistan, Afghanistan, Turki, Mesir, dan Indonesia yang menyasar penguasa atau kelompok lawan seperti Syiah dan penganut agama minoritas, apakah bisa disamakan dengan kasus bom bunuh diri di Palestina? Tentu tidak. Yang awal bermotif pembelaan atas tanah air dan perlawanan atas penjajah asing, sedang yang kedua bermotif konflik politik, ideologis, dan sektarian. Ideologis dalam arti pelaku memperjuangkan ideologi “Islam” sesuai yang dia pahami, dan menyerang lawan biasanya simbol pemerintah yang dianggap sekuler atau yang tidak beridentitas Islam. Dan disebut sektarian karena menyerang sekte lain yang menjadi rivalnya. Seperti serangan atas komunitas Syiah di Baghdad yang sedang menghadiri peringatan wafatnya Imam al-Kadhim (Imam ketujuh dari Ahlul Bayt), Juli 2016. Hal serupa terjadi beberapa kali sebelumnya yang memakan korban nyawa dan luka ratusan orang. Pelaku serangan diidentifikasi dari kelompok ISIS (sumber: Anadolu).
Dalam forum Bahtsul Masail NU dalam Munas Alim Ulama di Pondok Gedhe 2002, bom bunuh diri dibedakan antara dalam perang dan damai. Dalam kondisi awal dimungkinkan seperti dalam konflik Palestina. Sementara dalam yang kedua tidak dimungkinkan seperti dalam konflik ideologi dan sektarian antarpemeluk beda agama atau seagama atau antarkekuatan ideologi politik senegara atau lintas negara.
Syekh Ali Gomaah, ulama besar al-Azhar Mesir, menjelaskan bahwa serangan bunuh diri tidaklah dibenarkan. Hal ini lantaran mengabaikan larangan membunuh masyarakat sipil bahkan dalam perang yang sebenarnya sekalipun. Jika dia menyasar tentara atau polisi atau anggota militer, maka dia melanggar keumumam larangan bunuh diri dalam hadits: Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka Allah akan mengazabnya di hari kiamat (HR. Bukhari-Muslim). Ia juga melanggar prinsip “menghindari kerusakan diutamakan daripada mengejar kemaslahatan”.
Pertentangan ideologi yang semuanya untuk memperjuangan nasib umat Islam dan tegaknya syariat Islam, masih kalah nilainya dengan keselamatan nyawa dan keamanan bersama. Memperjuangan syariat banyak yang melakukannya sementara hilangnya nyawa tidak ada gantinya. Mengutip ucapan KH. Hasyim Muzadi jangan memperjuangkan yang tidak pasti (mawhum) dan meninggalkan yang pasti (muhaqqaq). Kerusakan yang diakibatkan oleh bom bunuh diri adalah pasti, sementara tuntutan yang diperjuangkan hingga mati belum tentu tepat. Dan jika iya, bisa dipastikan telah ada orang atau kelompok yang telah melakukannya bahkan lebih besar meski dengan cara yang berbeda.
Dalam argumen yang melarang serangan atas warga asing seperti para turis di Mesir, sang Syekh mengatakan bahwa dalam jihad perang, kalkulasi kemenangan harus diutamakan. Jangan asal perang jika besar kemungkinan kalah (www.draligomaa.com). Dalam 30 perang (ada yang mengatakan 19 karena perang yang berdekatan dijadikan satu) yang diikuti Rasulullah dan banyak yang tidak diikuti Rasulullah (sirriyah), umat Islam selalu menang kecuali Perang Uhud. Maka kalkulasi kekuatan harus mengemuka dan bukan semata emosional demi menegakkan kalimat Allah. Jika demikian, tidak salah jika Syekh Gomaah menyebut mereka dengan Ahlul Hawa atau budak hawa nafsu, atau ahlul bid’ah karena tidak mengikuti aturan syariat jihad, atau pemberontak (bughat).
Perang untuk menang bukan untuk kalah. Bukan asal mati syahid yang belum tentu syahid. Seperti dalam perang Khaibar di mana Rasulullah menyangkal kesyahidan seorang sahabat dan berkata: Saya melihatnya di neraka dengan burdah yang melilitnya (hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim). Atau yang mati dalam perang tapi ada riya agar dianggap pemberani dan pahlawan atau karena motif fanatisme. Yang seperti ini syahid di dunia tapi tidak di akhirat. Dikubur secara syahid tanpa dikafani tapi sebenarnya tidak demikian di mata Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang mati dalam perang bersama Rasulullah itu syahid. Apalagi perang yang tidak bersama Rasulullah yang tidak jelas tujuan dan nilai syariatnya. Apalagi dengan tujuan yang jelas terlarang seperti pemberontakan melawan pemerintahan yang sah atau bughat (al-Hujurat [49]: 9).
Dalam perang yang didahulukan adalah membangun kekuatan sehingga musuh gentar. Mayoritas perang zaman Rasul tidak sampai terjadi karena musuh takut dan kabur. Ada juga yang musuh akhirnya membubarkan diri karena faktor alam. Seperti perang Ahzab tatkala hembusan angin kencang melepaskan seluruh tenda-tenda musuh tanpa sisa hingga mereka tidak lagi kuasa untuk bertahan. Kekuatan yang melampaui musuh adalah awal yang harus dimiliki sebelum berperang. Bukan mendahulukan aksi angkat senjata dan memastikan diri kalah dengan bom bunuh diri. Apalagi jika musuh yang diserang adalah sesama Muslim yang hanya karena beda kelompok (sektarianisme) atau beda pandangan (ideologi), jelas jihad perang dalam hal ini adalah penyia-nyiaan nyawa manusia (ihdar al-dam). Padahal jelas bahwa membunuh manusia satu seperti membunuh semua manusia dan membela nyawa manusia satu laksana membela semua manusia (al-Maidah [5]: 32).
Al-Qurtubi merujuk pada Ibn Abbas menafsirkan membunuh satu nyawa seperti membunuh semua nyawa adalah nyawa nabi atau Imam adil. Membunuhnya sama dengan membunuh semua manusia karena besarnya peran bagi manusia banyak. Meski demikian dalam Tafsir al-Wasit, Muhammad Sayyid Tantawi menguatkan pandangan yang menafsirkan nyawa tersebut dengan nyawa manusia secara umum bukan nyawa tokoh tertentu. Artinya, membunuh siapa pun tanpa haq, adalah seperti membunuh semua manusia. Meski demikian, penafsirannya dengan nyawa imam adil atau penguasa mengandung arti pentingnya menjaga keselamatan pemimpin negara dan peringatan agar dalam melawan sistem penguasa dihindari menempuh jalan yang membahayakan umat Islam baik materi apalagi nyawa.
Achmad Murtafi Haris, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua