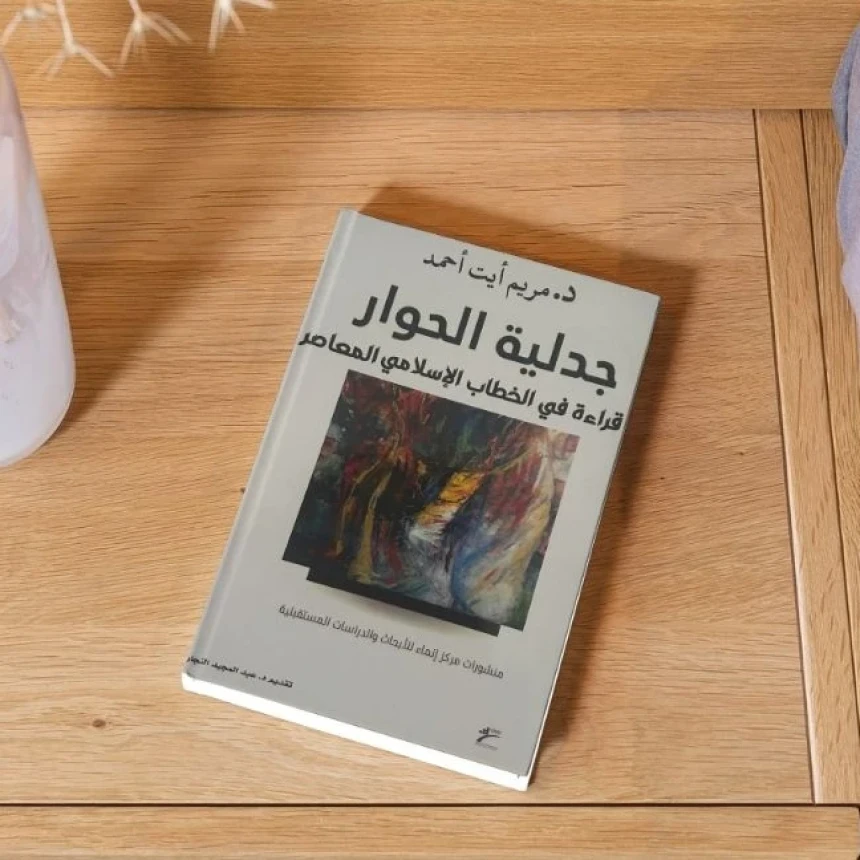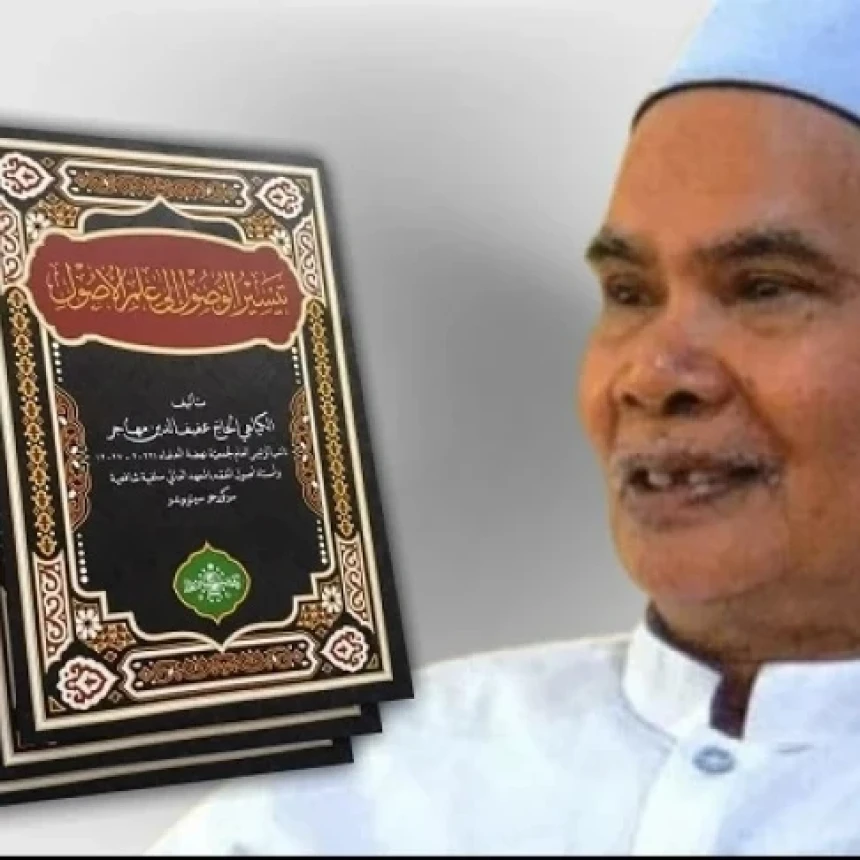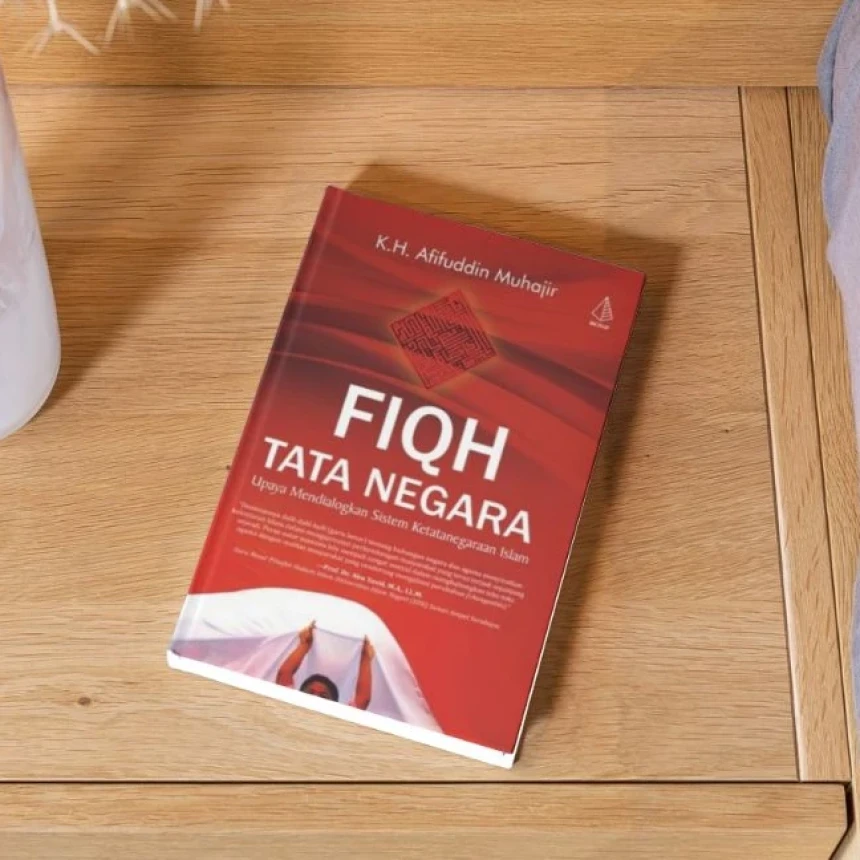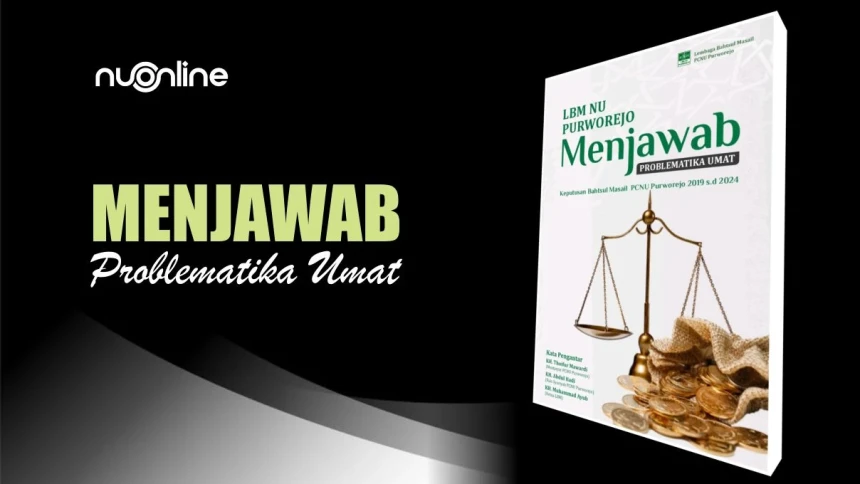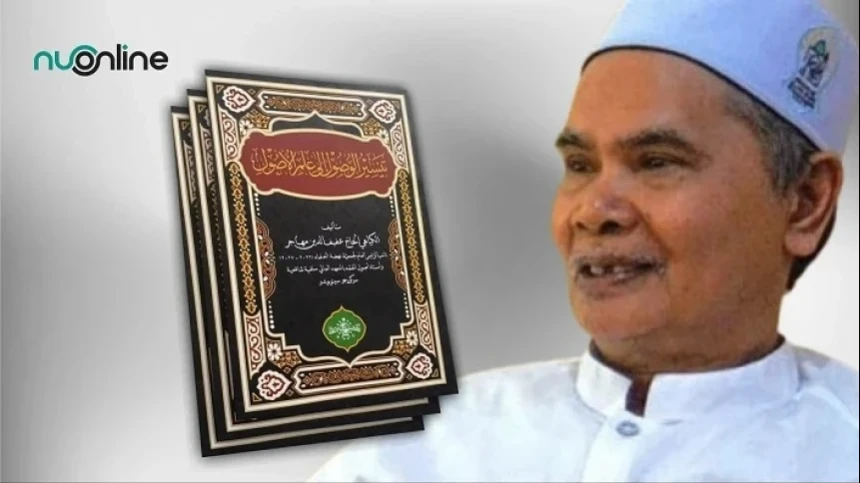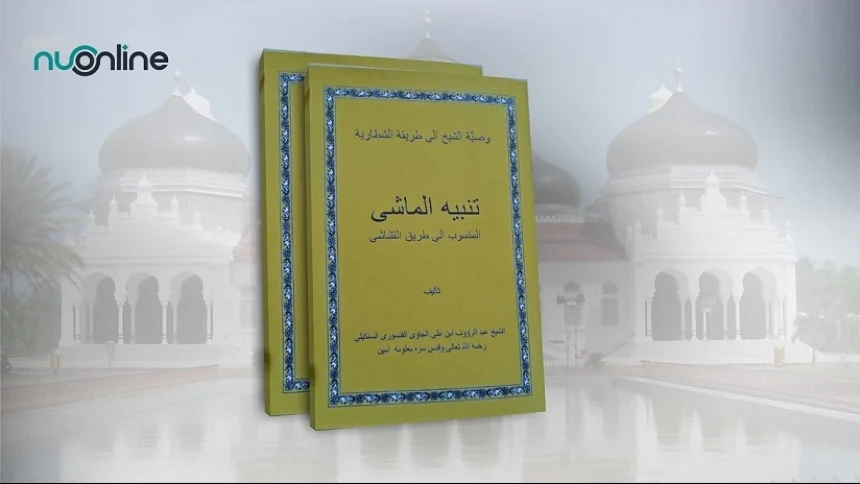Cetakan : 1, Juli 2005
Tebal : 260 halaman
Peresensi : Muhammadun AS*
Gendrang melawan korupsi dinegeri ini telah begitu bergemuruh dengan dideklarasikan berbagai lembaga untuk memberantasnya. Namun pemberantasan korupsi, tidaklah sebuah wacana saja yang di'deklarasikan' dihadapan publik, tetapi harus direalisasikan dalam tindakan konkrit yang dapat dilihat masyarakat. Memang, penetapan ini sangat penting untuk mengembalikan kembali semangat pemberantasan korupsi negara-negara yang selama ini terpuruk akibat dilanda kejahatan para koruptor yang sedemikian rupa. Wabil khusus Indonesia, negara yang dulunya dianggap sebagai bangsa yang ramah, santun, dan bersahaja dalam percaturan dunia, ternyata ramahnya hanya untuk mengelabuhi saudaranya sendiri dengan berkorupsi tanpa mengenal hati nurani.
Bahkan, hasil survey tahunan lembaga Political and Economic Risk Consultancy [PERC] tahun 2004, Indonesia di nyatakan sebagai negara terkorup sebagai Asia. Prediket sebagai negara terkorup sebagai Asia merupakan goncangan psikologis yang sangat menyakitkan di hati seluruh rakyat negeri ini, karena secara tidak langsung, yang terkena getah perbuatan keji ini adalah seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya para koruptor saja. Para koruptor malah dengan seenaknya melancarkan praktik korupsinya ditengah penderitaan saudara sebangsa dan sebagai Tanah Air.
Buku "Jihad Melawan Kor<>upsi" ini merupakan kesaksian para kaum intelektual yang prihatin dengan wajah kelam bangsa ini. Karena begitu suramnya bangsa ini, sampai-sampai Kwik Kien Gie dalam tulisannya dibuku ini bertutur dengan nada yang sangat menggigit, "Aku bermimpi menjadi koruptor". Kritik Kwick Kyan Gie tersebut bukanlah mimpi, namun telah menjadi realitas yan menggelut dalam dunia kebangsaan kita. Memang, kalau kita mencermati secara jeli, korupsi di negara yang tercinta ini telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Birokrasi pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah bahkan sampai para ke pelosok desa, korupsi seakan menjadi sebuah keniscayaan.
Semua sitem administrasi kepemerintahan sudah tidak bisa lagi dilepaskan dalam kungkungan budaya korupsi. Istilah-istilah tanda terima kasih, tali kasih, uang pelicin, dan uang lelah selalu diucapkan untuk memperhalus budaya korupsi. Pelayanan aparat negara kepada masyarakat selalu memunculkan praktik-praktik tersebut. Sehingga dalam benak masyarakat kita sekarang, praktik-praktik uang lelah dan lain sebagainya sudah menjadi budaya sehingga kemudian muncul perasaan tidak enak dan keharuasan melakukan penyuapan dan penyogokan, sekalipun itu merupakan penyelewengan.
Padahal kalau kita terus terang, pelayanan aparat negara kepada masyarakat merupakan keniscayaan sebagai tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Para birokrat sebetulnya adalah pelayanan masyarakat yang setiap saat harus siap melayani semua kebuhan masyarakat. karena bikrat dan pejabat negara adalah pengabdian kepada rakyat, bukan pemerasaan kepadanya [hal. 89].
Dalam konteks demikian, antara aparat pemerintahan dan rakyat telah terjadi kekuatan budaya yang akan semakin mematikan masa depan bangsa. Menurut Robert Klitgaard [2002], potensi korupsi melekat erat dengan kekuasaan. Maka tidaklah salah kalau Lord Acton menyebut kekuasaan cenderung korupsi. Ciri khas kekuasaan yang dapat diselewengkan antara lain. Pertama, kekuasaan yang terpusat atau sentralistik. Model kekuasan sentralistik dalam bangsa kita ini tercermin dari pemerintahan Orde Baru [Orba].
Semua urusan kepemerintahan pasa masa Orba selalau ada ditangan sang penguasa satu. dan pada masa Orba tidak ada satupun lembaga non-pemerintah yang berani melakukan counter kepada pemerintah. Kalaupun ada yang berani maka umurnya mereka tidak akan bertahan lama. Yang terjadi adalah sikap kesewenang-wenang dari aparat pemerintah untuk menghalalkan segala cara. Endingnya yang terjadi dewasa ini adalah maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN]. Penyakit KKN sampai sekarang masih menjadi penyakit yang sulit di carikan obatnya, karena mengakar dari pusat sampai kepelosok desa.
Kedua, lembeknya mental menghadapi bujuk rayu korupsi. Rapuhnya mentalitas ini lebih mengarah kepada aparat negara yang berwenang mengadili para koruptor, dalam hal ini aparat hukum. Hukum tidak lagi mampu menjerat para koruptor ke dalam sangsi yang sebenarnya. Justru yang terjadi aparat hukum sering melimpahkan kejahatan para koruptor pada pihak-pihak yang bersih dan tidak menahu. Mengapa demikian ? Karena aparat hukum kita tidak kuasa menahan nafsunya menerima uang yang melimpah dari para penjahat korupsi. Aparat hukum merelakan tugas suci untuk menegakkan keadilan, dan ditukarkan dengan uang-uang bertebangan disekelilingnya. Disini, uang menjadi raja di raja yang bahkan mengalahkan Tuhan yang diyakininya.
Ketiga, kemiskinan dan keadaan hidup yang menyakitkan yang dialami sebagian besar masyarakat mendorong orang mencari cara termudah, tercepat, yakni melakukan korupsi. Sifat pragmatisme seperti ini telah menjadi budaya masyarakat kita. Jabatan yang ditempati seseorang, seolah kesempatan yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa, karena pada suatu saat mereka nanti belum tentu mendapatkan kembali. Maka, jalan menumpuk kekayaan sebesar-besarnya tidak bisa dielakkan lagi. Sehingga, setiap pergantian pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan menjadi ajang pengerukan kekayaan sebesar-besarnya bukan untuk
Terpopuler
1
Hitung Cepat Dimulai, Luthfi-Yasin Unggul Sementara di Pilkada Jateng 2024
2
Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%
3
Hitung Cepat Litbang Kompas, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran
4
Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan
5
Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?
6
Ma'had Aly Ilmu Falak Siap Kerja Sama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
Terkini
Lihat Semua