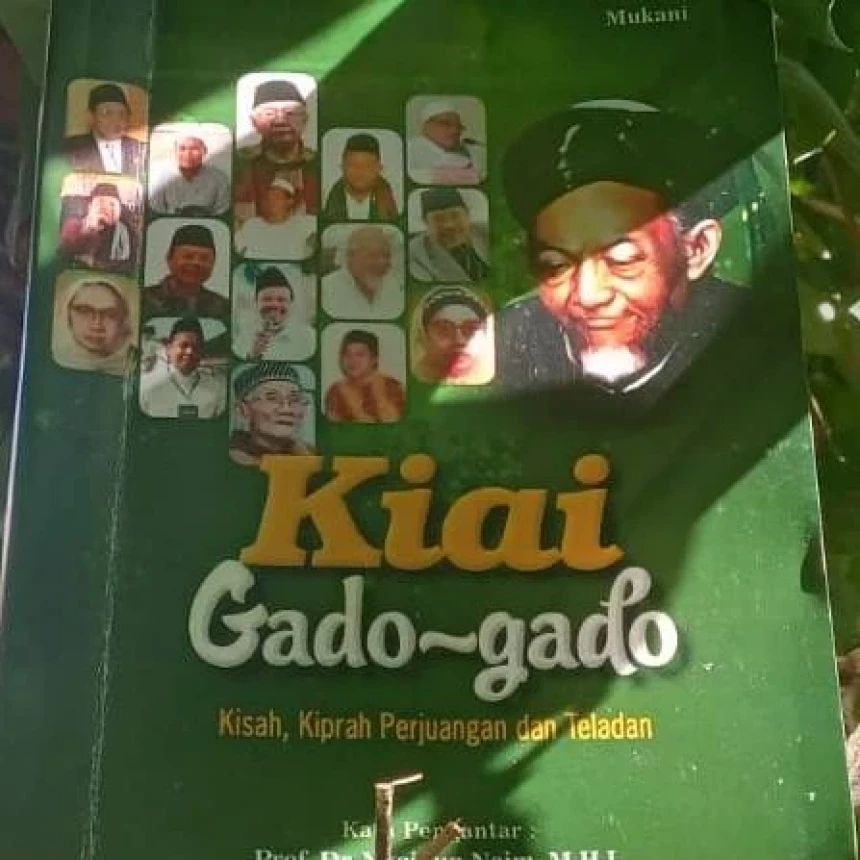Marzuki Kurdi (1): Manusia Kapur Menempuh Jalan Kiai Rakyat
NU Online · Kamis, 23 Oktober 2025 | 17:00 WIB
Nur Khalik Ridwan
Kolomnis
Pada 18 Oktober 2025 Kiai Marzuki Kurdi didahulukan oleh Allah untuk diantar ke perjalanan alam kubur, daripada rekan-rekan semasanya yang masih hidup. Saya mendengar kabar kewafatannya ketika sedang hadir agak telat (bersama Nurul Huda SA dan Ghufron Masduki) di acara haul 100 hari KH Moh. Imam Aziz, di Pesantren Bumi Cendekia, pada tanggal 18 Oktober 2025.
Adalah Ahmad Ghozi, aktivis NU yang agak berbahaya di Yogyakarta, memberi kabar kewafatan Kiai Marzuki itu, ketika ia sedang melakukan perjalanan untuk acara pernikahan Mukhibullah Ahmad di Magetan. Besoknya saya ke rumah Kiai Marzuki Kurdi di Tapanrejo, Sleman, dan masih mendapati serombongan sahabat dan murid Kiai Marzukui Kurdi yang baru saja mengantar ke makam.
Kiai Marzuki Kurdi merupakan sosok yang sangat disegani di Yogyakarta, dan sering kita panggil Kiai Marzuki Kurdi atau Pak Marzuki. Beliau merupakan referensi dari kiai-kiai rakyat di dalam lingkaran gerakan Yogyakarta yang tetap setia hingga akhir hayatnya: kiai yang setia menempuh “jalan kiai rakyat”.
Selebihnya, di antara manusia sezamannya ada yang mencampur jalan antara berdekatan dengan kekuasaan, bergiat di struktural NU, sebagian mencampurnya menjadi politisi gerakan, baik di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan; dan sebagiannya banyak diam untuk urusan-urusan publik.
Kiai Marzuki Kurdi tidak demikian, ia bersuara, tidak berbelok, kadang berada di balik layar dan mengorganisir, tetapi kadang langsung terjun, bahkan ketika sudah sakit di atas kursi roda sekali pun. Beliau mendidik kader dan mempertahankan soliditas dalam gerakannya, di tengah belantara Nahdliyin yang terpolarisasi. Diksi-diksinya meletup tetapi kokoh, bening dan jernih, dan layak diambil faedahnya, dibuang yang amat pedas. Kata-katanya khas, jelas dan tidak tedeng aling-aling. Dari beliau kita mendengar “manusia Jarkoni”, “cah loro bedhes”, “politisi gerakan”, dan sejenisnya. Akan tetapi sebagian diksinya, tentu tidak saya kutip di sini karena terlalu pedas.
Beliau disegani bukan karena pengaruhnya yang meluas di antara generasi di bawahnya, tetapi karena keteguhannya di “jalan kiai rakyat” ini, sehingga nyaris ditakuti: sedikit yang berani mendekat, tetapi juga dirindukan. Adik-adik di bawahnya, tidak semua mengenalnya. Hanya mendengar namanya. Apalagi generasi 200o-an ke atas, hanya sedikit yang mengenalnya, di lingkaran Mas Luji, Mas Tri, dan Mas Hadi Ismanto. Sementara generasi 1990-an yang mengenalnya cukup dekat, itu pun tidak banyak berada di dekatnya; dan yang seangkatan menemaninya adalah Mas Kiai Abdul Aziz Gambus, dan beberapa yang lainnya.
Lingkarannya, selain para alumni PMII, juga kelompok-kelompok yang bergiat di jaringan gerakan tani (jaringan Bina Desa, Patria Nusantara, SPI Yogyakarta, dan kemungkinan yang lainnya lagi), Gusdurian, MuhammadiNU, dan Gerakan-gerakan Nahdliyin. Terakhir kali, kami atas nama panitia mengontak beliau untuk menghadiri dan mengisi acara Mubes warga NU di Kampung Mataraman (2024) yang diselenggarakan anak-anak muda NU, dan sangat bersemangat. Katanya: “Jik urip, urip lan urip.”
Sebelumnya juga kita undang di acara Haul Gus Im di Joglo Pangurip dalam keadaan sudah berada di atas kursi roda, bersama Kiai Aziz Gambus. Sebelumnya lagi, juga janjian di acara Gusdurian, menunggu seorang kiai yang juga diundang dan akan “dikrek”, sayangnya sang kiai tidak datang.
Dari Sumurgung, Montong Tuban
Kiai Marzuki Kurdi berasal dari desa kecil bernama Sumurgung, Montong, Tuban. Wilayah ini ada di atas bebatuan-pegunungan kapur. Dan, beliau betul-betul anak kapur dari wilayah ini, yang ditempa kehidupan pesantren dan gerakan di Yogyakarta. Sang ayah, adalah Kiai Kurdi Sumurgung, pengasuh pesantren Mambaul Ulum, yang juga bekerja sebagai pedagang kapur (bahkan juga pembakar kapur).
Ibunya bernama Nyai Umi Kultsum, yang kuat bertirakat, dan dikenal memiliki ijazah wirid “bila masak suatu hidangan, akan mencukupi meski yang datang banyak.” Ketika saya ceritai soal ini, Kiai Semut Geni Pajangan Bantul, segera berkeinginan untuk berziarah ke wilayah ini. Entah kapan, bisa ziarah ke Kiai Kurdi dan Nyai Umi Kultsum: katanya mau direncanakan.
Kiai Kurdi berkiprah di wilayah Sumurgung sejak sekitar tahun 1960-an, mengasuh Pesantren Mambaul Ulum. Pesantren ini meneruskan tradisi dari pem-babad awal di wilayah ini, dari tokoh bernama Kiai Marzuki. Kiai Marzuki yang dikenal sebagai tokoh pertama yang babad alas ketika masih berupa langgar gladag, langar kuno, dikenang sebagai sesepuh. Perjuangan Kiai Marzuki dilanjutkan Kiai Kurdi (ayah dari Kiai Moh Marzuki Kurdi), meskipun menurut salah satu cucunya, beliau tidak memiliki hubungan garis nasab dengan Kiai Marzuki yang menyebarkan Islam dan mbabad langgar gladag di Sumurgung.
Kiai Kurdi berasal asli dari Sumurgung, demikian pula sang istri, Nyai Umi Kultsum. Dalam menempa tirakat, Kiai Kurdi melewati masa belajar ngelmu di Pesantren Kaliuntu, Jenu. Pesantren Kaliuntu ini termasuk pondok sepuh di Tuban. Selain itu Kiai Kurdi juga tabarrukan di Sarang, Tanggir, Tebuireng, dan beberapa pesantren lainnya. Pesantren Kaliuntu ini banyak mencetak hafidz, dibawah bimbingan Mbah Kiai Dimyathi Jenu. Setelah pulang ke Sumurgung, Kiai Kurdi meneruskan perjuangan Kiai Marzuki Sumurgung. Perjuangan Kiai Kurdi akhirnya diberkahi hingga bisa ngaji rutin di Masjid Sumurgung, meskipun gothakan-gothakan pondoknya belum dikembangkan.
Sang anak yang bernama Moh. Marzuki Kurdi lahir pada tahun 1956, dan ketika wafat umurnya mencapai 69 tahun. Beliau anak ke-3 dari 6 bersaudara dari anak-anak Kiai Kurdi dengan Nyai Umi Kultsum, yaitu: Siti Marhamah, Siti Aisiyah, Moh Marzuki, Maisarah, Khairiyah, Maryatun, dan Muawanah. Kiai Marzuki Kurdi dengan demikian anak ke-3 dan sangat diharapkan untuk meneruskan pesantren.
Karena hidup di lingkungan pesantren itulah, Marzuki Kurdi kecil belajar kepada ayah dan ibunya di Sumurgung: belajar kitab-kitab kecil dan menjalani tradisi pesantren. Sekolah formalnya ditempuh di MI dan MTs di Tarbiyatul Banin-Banat, satu kecamatan di desa sebelah Sumurgung. Setelah MTs, Kiai Marzuki melanjutkan pendidikan di Tambak Beras, untuk masuk jenjang Madrasah Aliyah di pesantren terkenal ini. Di Tambak Beras, menurut salah satu cucu Kiai Kurdi, Kiai Marzuki Kurdi satu ghotakan dengan salah satu tokoh Tuban, yang sama-sama ngaji di Tambakberas, bernama Fatkhul Huda. Semasa di Tambakberas pula, kiai-kiai yang menjadi pengasuh saat itu, di antaranya adalah KH Amanalullah, KH Djamal, dan yang seangkatan.
Moh. Marzuki Kurdi muda kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, di Fakultas Adab, asal fakultas dari sebagian besar para pendiri LKiS, yang diinisiasi oleh KH Fajrul Falaakh, seperti KH Imam Aziz, KH M Jadul Maula, Fikri AF, KH Amirudin Arrani, Eman Hermawan, Shaleh Isre, KH Nurudin Amin, dan sahabat-sahabat lainnya. Dalam gerakan di Kampus Putih ini Marzuki Kurdi muda berinteraksi masuk PMII bersama sahabat-sahabat lainnya, angkatan 70-an akhir dan 80-an awal, seangkatan dengan Kiai Abdul Aziz Gambus.
Di antara sahabat-sahabat Kiai Marzuki Kurdi yang memberikan pengakuan, di antaranya ada senior Andy Muawiyah Ramly, yang kemudian membuat kesaksian dalam tulisannya berjudul “Kiai Marzuki Kurdi” (18 Okrober 2025) yang beredar di grup WA. Ketika di IAIN beliau disebut, pernah memimpin Teater Kupu-Kupu, dan sangat menghormati Mas Kartjono, Mas Willy, KH Abbas Muin, dan tentu saja Gus Dur juga Gus Im.
Waktu selesai kuliah, sang ayah (Kiai Kurdi) mengharapkan Kiai Marzuki Kurdi muda agar pulang mengembangkan pendidikan dan Pesantren Mambaul Ulum, Sumurgung. Hal ini diceritakan Kiai Marzuki Kurdi kepada keponakannya dan cerita Kiai Kurdi sendiri kepada sebagian cucunya. Karena saat itu, pondok di pegunungan kapur Tuban ini belum memiliki ghotakan-gothakan yang mencukupi. Sementara rutinan malam Selasa dari Kiai Kurdi selalu dipenuhi banyak jamaah.
Sang ayah, Kiai Kurdi yang memberi pengajian kitab-kitab pesantren di Masjid Sumurgung ini, memang mengharapkan kepada anak laki-laki satu-satunya ini agar pulang ke Sumurgung. Nasib menghendaki lain, Marzuki Kurdi muda memilih pergi ke Jakarta bersama sahabat-sahabatnya, dan berada di lingkaran dekat Gus Dur setelah diputuskannya Khittah NU tahun 1984.
Setelah agak lama di Jakarta, di LKPSMNU-Lakpesdam dan membangun jaringan dengan Bina Desa, beliau memilih tinggal di Yogyakarta, membina rumah tangga dan mewariskan keteguhan dalam menjalani hidup di “jalan kiai rakyat”: ingat ini bukan bukan nama jalan, seperti Jl. Solo dan sejenisnya. Kalimat menempuh “jalan kiai rakyat” adalah jalan khidmah yang dekat dengan rakyat, tidak mempolitisasi rakyat dan gerakan, dan terus setia bersama rakyat bawah. Di Yogyakarta, beliau mengorganisir anak-anak muda yang terlibat di SPI, jaringan Bina Desa, dan aktif di Patria Nusantara, selain terlibat di gerakan-gerakan kultural Nahdliyin lainnya.
Manusia Kapur, Mengaji dan Meneladankan Keteguhan
Kehidupan di kampung Sumurgung, disebutkan oleh penuturan sebagian cucu Kiai Kurdi adalah bersawah tadah hujan. Melalui sawah tadah hujan ini, ekonomi Sumurgung bergerak bersamaan dengan ketrampilan membakar batu kapur. Bahkan, keseharian Kiai Kurdi selain khidmah mengasuh pesantren dan ngaji di tengah masyarakat, juga diakui sebagian cucunya, juga membakar kapur dan menjual batu kapur. Tradisi manusia kapur ini menjadi identik dengan Sumurgung.
Air mengalir yang dimanfaatkan, dulunya di Sumurgung ini ada kali dengan sumber yang gede, meskipun daerahnya berkapur. Sungai atau kali ini alirannya dari atas, dinamakan Kali Lowo (atau Lowong). Ketika tidak ada hujan Kali Lowo itu masih ada air yang cukup besar, makanya disebut “Sumurgung”. Tetapi kini sudah tidak seperti itu lagi. Belakangan selama 20 tahun terakhir kali itu sudah kering bila tidak ada hujan. Hal ini mengharuskan masyarakat mengusahakan air bila tidak ada musim hujan.
Ketika Marzuki Kurdi kecil dan remaja, yang air kalinya masih mengalir itu, sering minum air kapur di sini, bermain-main, sambil menyaksikan kesungguhan masyarakat bertani tadah hujan, dan membakar kapur. Menyaksikan para petani tadah hujan dan pembakar kapur bekerja, mewariskan semangat batin.
Seiring dengan surutnya para pembakar kapur karena ada mesin-mesin besar yang membuat kapur, surut pula ketrampilan membakar kapur. Sebagai remaja dan pemuda yang menyaksikan daerahnya semacam itu, namanya Marzuki Kurdi, yang telah minum air kapur dan menjadi manusia kapur dari kapur Sumurgung ini. Hal itu menjadikannya teguh menghadapi perubahan.
Ditempa dalam kehidupan masa kecil dan remaja oleh keadaan tanah yang berkapur, dan air kapur, dan sawah tadah hujan, menjelaskan suatu ekologi hidup: medan yang tak mudah. Hal seperti ini pernah saya saksikan sendiri ketika sebagian keluarga kami, juga menanam di sawah tadah hujan di barat gunung Kumitir, betapa tidak mudah melakoni kehidupan seperti ini. Ditambah lagi dengan tanah yang berkapur: medan yang menempa anak-anak kapur, tentu saja bertambah lebih berat, mengharuskan dinamis dan prigel menjadi “manusia kapur”, mengusahakan air, dan memenuhi ekonomi keluarga.
Kondisi kehidupan yang seperti ini menempa anak-anak remaja Sumurgung masa 1960-an, dibarengi dengan penanaman nilai-nilai santri desanya. Sang ayah (Kiai Kurdi), menanamkan nilai-nilai kesungguhan, berjuang batin dalam segala keadaan, dan tentu saja, manfaati tumrap liyan, kepada para murid dan anak-anaknya. Keteladanan sang ayah mewarnai ingatan watak dan jangkar kabudayaan Kiai Marzuki Kurdi kecil dan remaja sebagai manusia yang berasal dari tanah kapur.
Dalam mengaji di pesantren Sumurgung, kitab-kitab kecil yang dibaca sang ayah, seperti Aqidatul Awam, al-Iklil, dan sejenisnya, menurut sebagian cucunya, disampaikan dengan referensi dari banyak sumber kitab dan kearifan. Hal ini memperluas wawasan cakrawala dalam pengajian sang ayah. Kadangkala dalam pengajian sang ayah juga ada yang bertanya, sehingga mewarnai kehidupan dinamis pengajiannya: “pengajian kitab ada yang tanya?” Sungguh penanaman nilai-nilai di Sumurgung ini, menjadikan ingatan kelak dalam dinamisasi pencarian Kiai Marzuki Kurdi muda akan makna hidup dan tauhid.
Salah satu dzikir yang dilanggengkan kepada murid-murid Kiai Kurdi adalah membaca Shalawat Burdah, Maulaya shallii wasallim daa’iman abadaa… Wirid ini diteruskan sampai sekarang ketika santri-santri mau masuk sekolah di Pesantren Mambaul Ulum. Pantesan, sesekali bersama Kiai Marzuki Kurdi, lirih aku mendengarkan lantunan burdah ini. Sementara rutinan malam Selasa yang diampu Kiai Kurdi, di dalam tradisi Sumurgung sering disebut dengan “Berjuang Batin”, sebagaimana dituturkan sebagian cucu Kiai Kurdi. Maknanya adalah berjuang di tengah tanah kapur, sawah tadah hujan, relasi masyarakat, air yang langka, khidmah kepada masyarakat, dan membangun masa depan, berlandaskan nilai-nilai Islam, untuk mengabdi kepada Allah.
Pada masa 1960-an, ketika Kiai Marzuki Kurdi masih kecil, sekolah MI sudah dibangun di Sumurgung, baru kemudian MTs dibangun lama setelah itu, tahun 1987. MI Sumurgung yang sudah cukup tua ini adalah MI kedua di wilayah ini, setelah MI di Desa Jetak. Di Desa Jetak ini nama Kiainya adalah Kiai Khusnan Ali, yang juga sahabat dari Kiai Kurdi. Pada masa 1960-an, Kiai Khusnan pernah menjadi Ketua Tanfidziyah MWCNU dan Kiai Kurdi Sumurgung adalah Rais Syuriyah MWCNU di Kecamatan ini (Montong).
Pendirian sekolah di Sumurgung ini, berdasarkan informasi dari sebagian cucunya adalah atas kesepakatan dari para pengurus MWCNU, ketika sekolah yang ada di Jetak daya tampungnya sudah melebihi kapasitas. Pendirian sekolah di Jetak yang lebih dulu dari Sumurgung ini pun, juga berdasarkan musyawarah dari tokoh-tokoh di MWCNU Montong, yang salah satu tokohnya adalah Kiai Kurdi Sumurgung dan Kiai Khusnan Ali Jetak.
Dua orang itu menjadi tokoh NU setempat. Dua tokoh itu menurut informasi dari salah satu cucu Kiai Kurdi, juga menjadi tokoh PPP setempat pada masa awal partai itu didirikan. Pada masa 1960-an sampai 1970-an secara nasional, NU awalnya menjadi partai sendiri pada Pemilu 1971. Setelah itu, ada keinginan dari pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan partai-partai, sampai terbentuk PPP dan PDI. NU kemudian menarik diri dari partai politik pada tahun 1984. Kiai Marzuki Kurdi remaja menyaksikan perhelatan politik itu di kampungnya, ketika NU menjadi partai sendiri sampai terbentuknya PPP, ia masih mengunjungi rumahnya di sela-sela mondok di Tambakberas dan kuliah di Yogyakarta.
Selain itu, Kiai Kurdi, sang ayah, juga memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh di Tuban, seperti dengan Kiai dari PP Sunan Drajat, KH Ghofur, meskipun umurnya lebih tua Kiai Kurdi. Menurut cerita sebagian cucu Kiai Kurdi, sang kakek juga dikenal sering memasok batu kapur dan kayu kelapa untuk pembangunan beberapa pondok di luar Sumurgung. Hal ini mewariskan sikap khidmah, kerja keras, dan kerja-kerja gerakan, dan silaturahmi dalam mental ingatan Kiai Marzuki Kurdi remaja dan muda.
Dalam lanskap tanah berkapur, pertanian tadah hujan, nilai-nilai pesantren, dan politik masa NU menjadi partai sendiri itulah Kiai Marzuki Kurdi hidup di kampungnya, atau masih terhubung intens dengan kampungnya. Adonan nilai itu membentuk watak dan mentalnya yang dibarengi dengan “pencariannya” pada masa berikutnya ketika ia bergumul di Tambakberas dan Yogyakarta. Hingga Kiai Marzuki Kurdi muda benar-benar menjadi “manusia Kapur” yang telah menjemput takdir masa depannya, dengan watak khas yang teguh, dan tetap menjadi Nahdliyin.
Kiai Marzuki Kurdi, saya sebut seorang “manusia kapur”, yang tetap mengaji dan meneruskan nilai-nilai pesantren ketika ia pindah ke Yogyakarta, dari Tambakberas. “Manusia Kapur” itu terus mencari ilmu dan membuktikan ilmunya, karena cintanya kepada Allah, Kanjeng Nabi, NU, dan masyarakat kecil, dan menemukan minumannya dari “air kapur batin”, setelah ditempa oleh “air kapur lahir” di Sumurgung, tatkala kecil dan remaja. Sesekali saya bermimpi menyaksikan beliau berjalan di mega-mega, berkat minuman air kapur batin itu.
Bagi orang tarekat, kapur, minum dari air kapur, sebagaimana dijelaskan Syeh Abdul Qadir al-Jilani dalam takwilnya adalah kejernihan, yang melambangkan “bardul yaqin”, yaitu telah mengendapnya keyakinan kuat kepada Allah dalam pencapaian tauhidnya. Bardul yaqin itu minuman dari para al-abrar dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Insan [76]: 5, “sesungguhnya al-abrar minum dari gelas yang campurannya air kapur.” Sifatnya teguh, jernih, dan putih.
Keteguhan Kiai Moh. Marzuki Kurdi dalam menyangga “jalan kiai rakyat” di kemudian hari, telah sejak awal difondasikan dari minuman “air kapur lahir” di Sumurgung, yang dilanjutkan dengan minum “air kapur batin”, yaitu bardul yaqin dalam laku perjalanan hidupnya. Keteguhannya, mewariskan ingatan akan menjauhi jalan para “manusia Jarkoni”, “cah loro bedhes”, menampik jalan “politisi gerakan”, menampik jalan berbelok arah dari kiai yang akan “dikrek” di acara Gusdurian itu, mengisyaratkan ada mereka yang melakukan “politicking dalam gerakan”. Diksi-diksi lainnya, yang terlalu keras, tentu tidak saya kutip di sini.
Di tengah para manusia sezamannya yang yang terpolarisasi, dan sebagian berbalik arah, Kiai Moh. Marzuki Kurdi tetap setia berada di “jalan kiai rakyat”sebagai “manusia kapur”. Mewariskan keteladanan kepada generasi berikutnya: generasi penerus perlu memiliki keteguhan dan kekuatan dalam memperjuangkan prinsip, sebagai perwujudan manunggal-tauhid. Jalan “manusia kapur” yang demikian bukan khas terbentuk dari asal tanah kapur lahir yang menjadikan Kiai Marzuki menjadi “manusia kapur”. Manusia kapur bisa muncul dari segala jenis tanah asal manusia, asalkan ia mau meminum terus menerus “kapur batin” keteguhan dalam tauhid dan menjalan “jalan kiai rakyat.”(Bersambung)
Nur Khalik Ridwan, aktif di Syuriyah Ranting NU Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan penulis buku-buku tenang sejarah Jawa-Islam
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua