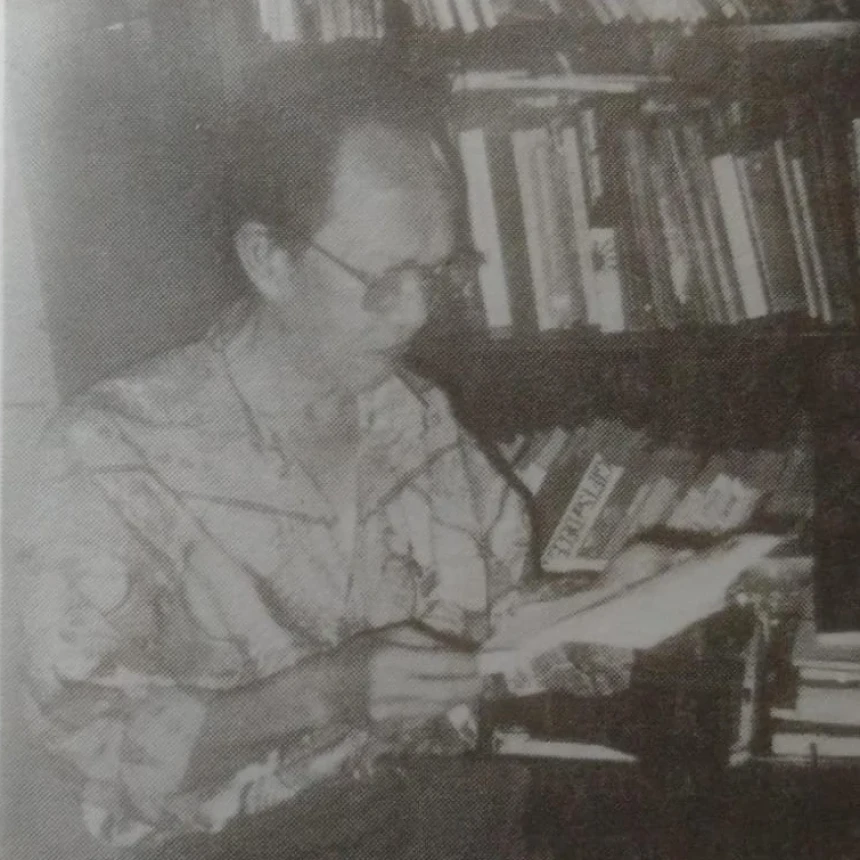Joko Priyono
Kolomnis
Mahbub Djunaidi (Bung Mahbub) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah dua wajah intelektual Nahdlatul Ulama (NU) pada masanya. Hingga kematiannya, mereka berdua dikenang oleh banyak orang, salah satunya dengan karya-karya yang pernah dituliskannya.
Bung Mahbub lahir pada 27 Juli 1933, sementara Gus Dur punya dua tanggal kelahiran, yakni 4 Agustus dan 7 September 1941. Selisih umur delapan tahun, menjadikan hal menarik dalam menilik hubungan antara kedua sosok pada masanya. Bung Mahbub wafat pada 1 Oktober 1995 sementara Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009.
Bung Mahbub dan Gus Dur memiliki sebuah kesamaan sebagai sosok yang “menulis”. Kerja intelektual itu menjadi bagian mengenai konsep maupun gagasan keberpihakannya terhadap banyak hal dalam situasi dan kondisi sosial yang mereka alami.
Mereka adalah representasi cendekiawan sejati, yang kalau meminjam bahasanya Romo Mangunwijaya di tulisan berjudul “Cendekiawan”, berupa orang yang tidak mencari menang, tetapi mencari kebenaran, orang yang tidak mencari enak, tetapi yang baik untuk kepentingan banyak orang, dan orang yang tidak gentar terhadap bentuk ancaman kekuasaan, tetapi ia arif, berhati-hati, dan waspada.
Empat tahun berlalu, kita kehilangan salah satu cendekiawan yang berpengaruh di Indonesia, Jakob Oetama. Dedikasinya terhadap Mahbub tatkala memperingati 100 hari berpulangnya si Bung, tulisan Mahbub selama di rubrik Asal Usul yang dimulai pada 23 September 1984 hingga 23 November 1986 diterbitkan Kompas menjadi sebuah buku utuh berjudul Asal Usul (1996). Di sana Jakob Oetama memberikan sedikit kata pengantar dengan menyebut sosok Mahbub meninggalkan dan mewariskan gaya jurnalistiknya sendiri.
Tak ayal, saat kepulangannya, Gus Dur mengenang sosok kelahiran Betawi tersebut sebagai kakak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana liputan dalam harian Pikiran Rakyat edisi 10 November 1995, Gus Dur menyampaikan, “Di Masa Orde Lama, Mahbub yang waktu itu merupakan guru dan kakak saya di lingkungan anak-anak muda NU, sudah memikirkan tentang suatu masa kelak. Masa yang dipikirkan dimaksudkannya ternyata menjadi kenyataan yakni Orde Baru, tentu kita tidak tahu, ketika beliau masih hidup di masa Orde Baru, tentu sudah memikirkan kelak akan ada masa lain di Indonesia.”
Humor dan Seni Tertawa
Mahbub dan Gus Dur punya banyak kesamaan ketika ditilik lebih mendalam. Selain sama-sama sebagai pemikir dengan sederet kolom dan karya lain yang pernah ditulis dan pribadi pembaca yang ulung, mereka berdua adalah pribadi yang identik dengan kelakar dan humor dalam menjalankan banyak aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Mereka punya sebuah seni dan cara tersendiri dalam membahas urusan pelik kemudian menjadikannya sebagai hal ringan yang penuh tawa, humor, dan tidak menghilangkan esensinya.
Interakasi langsung antara keduanya, salah satunya pernah terekam dalam catatan kecil melalui buku berjudul Uniknya Kak Abo: Mahbub Djunaidi di Mata Adiknya (Buku Revolusi, 2020) karya Fadlan Djunaedi. Fadlan yang merupakan adik dari Mahbub dikenal sebagai salah orang yang setia menemani dalam banyak aktivitas Mahbub semasa hidup. Seperti di antaranya pertemuan Mahbub dengan sederet tokoh penting nasional hingga saat di mana Mahbub menjadi tahanan politik di Rumah Tahanan Nirbaya pada masa Orde Baru.
Baca Juga
Selera Musik Para Kiai Nahdlatul Ulama
Sebuah momen pertemuan antara Bung Mahbub dan Gus Dur yang diceritakan oleh Fadlan lewat buku itu yakni saat tahun 1979 yang mana waktu itu Mahbub meminta Gus Dur untuk menjemputnya di kantor PBNU yang terletak di daerah Kramat Raya, Jakarta. Saat di tengah perjalanan sampai di daerah Sarinah, Gus Dur terceletuk pertanyaan
“Ka Abo, itu gedung apa?”
“Nggak tahu Man, kemarin pas ane lewat sini, belum ada. Masih rata tanah. Hebat Jakarta, tau-tahu dah jadi gedung aje,” Mahbub menjawab.
Celetuk percakapan yang ringan, santai, dan guyonan tersebut tentunya menyiratkan makna akan sebuah realitas yang terjadi. Akan bagaimana wujud kota Jakarta yang makin hari makin sesak dipenuhi gedung yang mencakar langit dan kebisingan lainnya akibat akumulasi dari sentralisasi. Walau demikian, Gus Dur yang terlihat ter-skak kemudian hanya terkekeh dan terlihat gemas dengan bahasa Jawa, “Iyo..Iyo aku lali. Sing aku ajak ngomong mantan ketua PWI dan pensiunan DPR.”
Humor menjadi sebuah parameter terhadap kewarasan hidup. Sebagaimana dijelaskan Gus Dur dalam kata pengantar untuk buku terjemahan Batara Sakti berjudulkan Mati Ketawa Cara Rusia (Grafiti, 1986) karya penulis dari Rusia, Z. Dolgopolova. Gus Dur yang dikenal juga sebagai “Kiai Kata Pengantar Buku” itu menjelaskan, bahwa rasa humor dari sebuah masyarakat mencerminkan daya tahannya yang tinggi di hadapan semua kepahitan dan kesengsaraan. Humor kemudian menyiratkan sublimasi dari kearifan sebuah masyarakat.
Konteks Sekarang
Akan tetapi, mungkin saja situasi demi situasi realitas kadang berbeda. Seperti halnya dirasakan banyak kalangan di akhir-akhir ini, yang mana berkerumun rombongan yang mudah baperan, tak tahu apa humor sejati itu bagaimana, dan yang terjadi justru kemarahan dan diskriminasi dengan kolotnya. Fenomena tersebut dapat dilihat di kalangan para komedian yang menyuarakan pendapatnya, terkadang dihajar habis-habisan oleh pihak tertentu, tak terkecuali dari penguasa. Dalam arus teknologi digital, serangan tersebut, kini lazim lewat pentungan oleh kelompok pendengung (buzzer).
Fenomena tersebut mengingatkan atas apa yang pernah terjadi di masa Orde Baru tatkala negara mudah memberikan cap “subversif” maupun “durhaka” terhadap mereka yang dipandang berbeda haluan dengan negara. Itu jelas tergambarkan oleh Michael van Langenberg dalam tulisannya, “Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, dan Hegemoni” yang termaktub di buku Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (Mizan, 1996).
Langenberg menyebutnya akibat kontrol negara yang mengambil peran relasi antara sistem terhadap masyarakat dengan kesepakatan hegemonik. Sungguh, bagaimana kita itu perlu memahami pikiran-pikiran Bung Mahbub dan juga Gus Dur.
Pada akhirnya, Bung Mahbub dan Gus Dur adalah dua tokoh jenaka yang masih menyimpan rahasia-rahasia. Maka, memperingati kematiannya bukanlah sebuah hal yang sia-sia. Sebagaimana menjadi tradisi di lingkungan jemaah Nahdlatul Ulama (NU) dengan mengadakan haul yang disertai pembacaan Yaasin, tahlil, dan doa-doa lainnya. Tak ada yang menjamin sampai dan tidaknya memang, tapi mengingat kematian seorang sebagai bentuk akan penghormatan dan menimba pada sumur keteladanan dari apa yang pernah mereka lakukan. Dan kita mungkin akan berucap, “apalah arti kehidupan, kalau tidak untuk ditertawakan?”
Joko Priyono, Fisikawan Partikelir dan Budayawan. Penulis Buku Bersandar pada Sains (2022).
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua