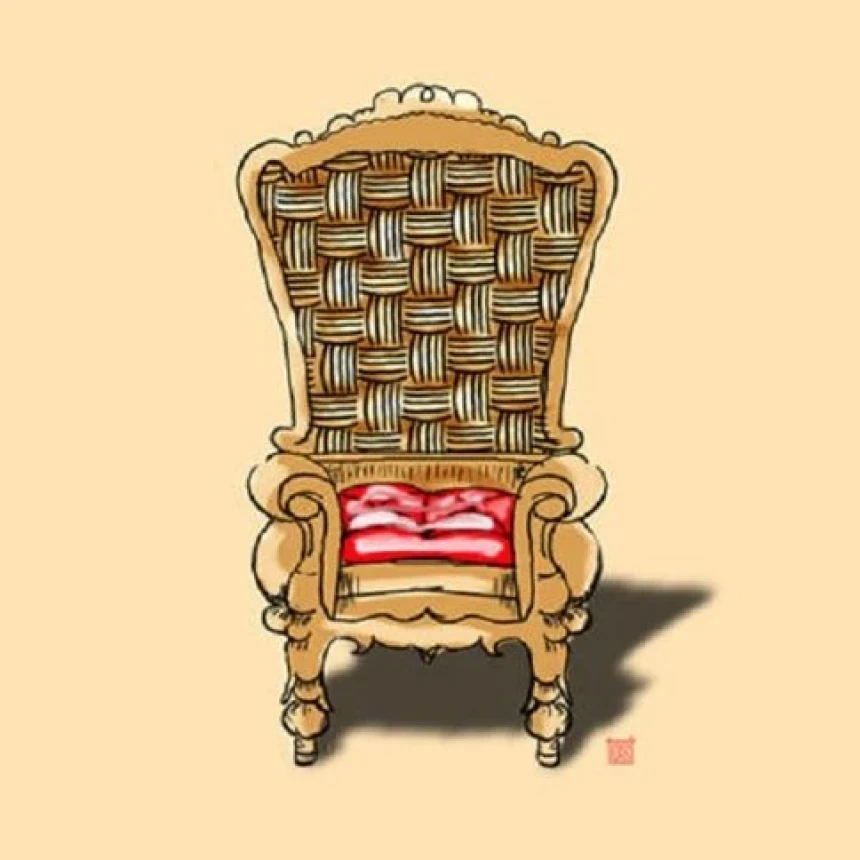Demokrasi Indonesia Bertumpu pada Masyarakat Sipil, Bukan Negara
NU Online · Rabu, 24 September 2025 | 21:30 WIB

Pakar pemilu dan demokrasi, sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini. (Foto: instagram Titi Anggraini)
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pakar pemilu dan demokrasi, sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menilai hampir semua lembaga independen di Indonesia saat ini tidak lepas dari intervensi politik. Kondisi ini, menurutnya, menjadi ancaman serius bagi resiliensi demokrasi.
"Setelah saya pelajari selama 17 hari di Australia, hampir semua institusi integritas yang mereka miliki juga ada di Indonesia. Kita punya KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, Dewan Pers, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas semuanya ada. Tapi masalahnya, semua institusi itu mengalami politisasi," kata Titi dalam webinar yang digelar secara daring pada Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan sejak awal reformasi lembaga-lembaga negara independen dirancang sebagai cabang keempat untuk memperkuat check and balance, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan. Namun dalam praktik hari ini, proses rekrutmen hingga kinerja lembaga tersebut sudah penuh warna politik.
Titi juga menyinggung dua peristiwa krisis demokrasi yang ia sebut sebagai “Prahara Agustus”. Pada 2024, parlemen secara terbuka menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Setahun kemudian, pada Agustus 2025, muncul eskalasi ketidakpuasan akibat semakin hilangnya representasi politik rakyat.
"Wakil kita hari ini seolah-olah hanya baik untuk hal-hal yang tidak pernah kita rasakan. Untuk hal-hal yang substansial, representasi itu semakin jauh," ujarnya.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada partai politik dan sistem pemilu yang gagal melahirkan representasi rakyat. Ia mencontohkan sejumlah negara yang bahkan mulai menguji alternatif representasi melalui citizen assembly sebagai jawaban atas krisis kepercayaan.
Titi juga menyoroti mandeknya legislasi pemilu. Padahal, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah ditetapkan sebagai prioritas legislasi 2025, namun hingga September belum ada draf akademik maupun rancangan yang jelas.
“Bayangkan, berapa banyak waktu kita buang untuk sebuah persoalan hulu demokrasi, tapi revisi undang-undang pemilu tak juga dibahas. Yang muncul justru Perpu darurat yang diisi insentif bagi partai politik, seperti tetap memakai nomor urut lama,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan penyelenggara pemilu juga banyak menyimpang. Mulai dari aturan keterwakilan perempuan yang tidak ditegakkan, penataan dapil yang mengabaikan putusan MK, hingga PSU (pemungutan suara ulang) yang merugikan keuangan negara.
"Saya menyebut KPU kita saat ini adalah KPU yang paling banyak merugikan keuangan negara," ujarnya.
Peran Masyarakat Sipil
Meski demikian, Titi menilai masih ada ruang resiliensi demokrasi yang bisa dijaga, yakni peran masyarakat sipil, media, dan pengadilan. Ia mencontohkan, putusan MK soal penghapusan presidential threshold hingga pemisahan pemilu nasional dan daerah lahir dari dorongan kelompok mahasiswa dan aktivis hukum.
“Resiliensi pemilu kita bertahan karena ada masyarakat sipil, media, dan pengadilan. Universitas harus menjadi teman bagi gerakan masyarakat sipil, kaderisasi aktivisme orang muda harus lahir dari kampus,” tegasnya.
Ke depan, Titi mendorong adanya rekonstruksi sistem pemilu dengan model campuran, penguatan kaderisasi partai politik, serta pembatasan masa jabatan ketua umum parpol.
“Kalau ingin menaikkan subsidi negara untuk partai, harus disertai sistem integritas yang jelas,” pungkasnya.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
6
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Terkini
Lihat Semua