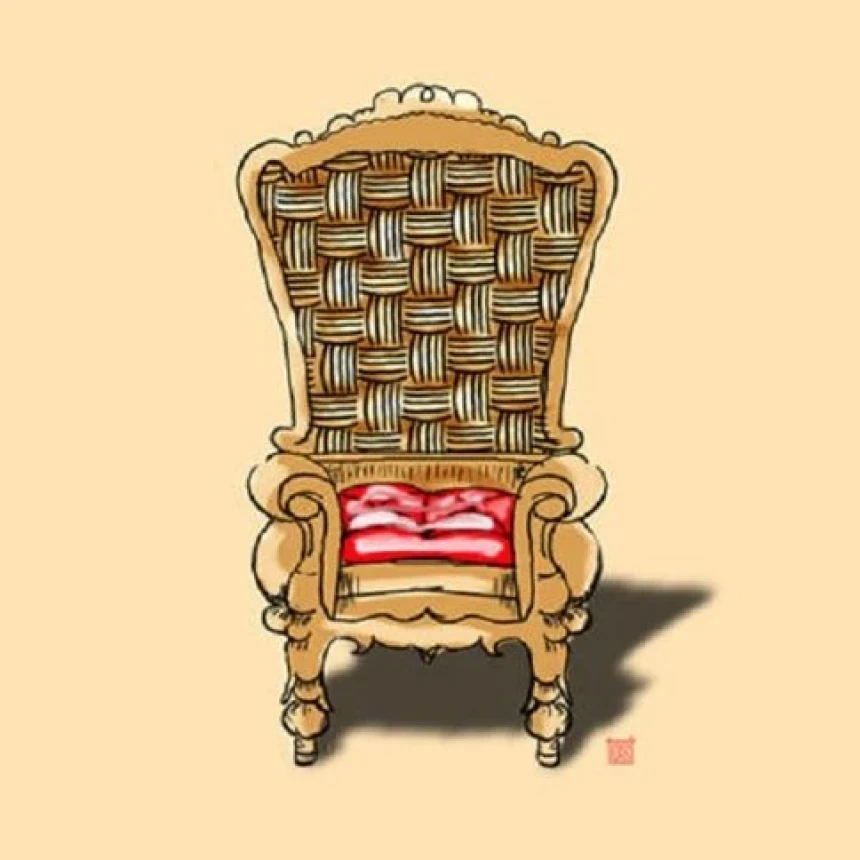Pilkada oleh DPRD: Efisiensi atau Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat?
NU Online · Rabu, 14 Januari 2026 | 22:48 WIB
Mahbub Ubaedi
Kolomnis
Wacana pilkada dipilih oleh DPRD kembali mengemuka, ini seperti menyaksikan dejavu politik yang kurang menyenangkan. Seperti menyaksikan ulang tahun gagasan lama yang dulu sempat dikubur oleh reformasi, lalu kini dihadirkan kembali dengan wajah baru, bahasa baru, dan alasan yang terdengar lebih rasional.
Rakyat, kata sebagian pihak, sudah terlalu capek. Negara juga terlalu boros. Politik lokal dianggap ribut, mahal, dan sering berakhir dengan konflik yang tidak elegan. Maka muncul solusi praktis nan ringkas, kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD.
Usulan ini seperti obat pereda instan. Sekali telan, sakit kepala politik seolah hilang. Namun seperti banyak obat pereda nyeri, ia kerap memiliki efek samping, seperti kantuk dan sebagainya. Bahkan kalo dikonsumsi berkali-kali, pelan-pelan bisa saja menggerogoti organ tubuh lainnya.
Sayangnya, dalam urusan demokrasi, efektivitas sering kali dibeli dengan menukarkan partisipasi, dan efisiensi dibayar mahal oleh kedaulatan rakyat.Wacana ini bukan sekadar ide administratif belaka, ini menjadi pertanyaan paling fundamental tentang siapa yang berdaulat dalam demokrasi kita, rakyat atau elit partai?.
Konsistensi yang Hilang
Ada satu kebiasaan lama dalam politik di negeri ini yang patut dicatat sebagai bagian dari folklore demokrasi. Ingatan partai politik sering kali lebih pendek daripada ingatan rakyat. Hari ini mereka berdiri di satu sisi sejarah, esok hari bisa berpindah ke sisi lain, sambil berharap publik lupa bahwa mereka pernah berpidato dengan arah yang berlawanan. Wacana pilkada oleh DPRD adalah contoh terbaru dari seniman politik dalam panggung demokrasi.
Ambil contoh, Partai Demokrat sebagai ilustrasi. Dulu, ketika pilkada langsung nyaris dikubur, partai ini berdiri paling depan sebagai penjaga “roh reformasi”. Pilkada langsung dipuji sebagai cara paling jujur untuk mendengar suara rakyat, sekaligus pagar agar kekuasaan tidak kembali ke ruang-ruang tertutup.
Kini, nada bicaranya lebih lembut dan hemat kata, efisiensi, stabilitas dan efektivitas. Bukan salahnya berubah pikiran, yang ganjil justru ketika perubahan itu disajikan seolah tidak pernah ada pidato lama yang dahulu dielu-elukan sebagai sikap negarawan.
Golkar barangkali paling tenang menghadapi perubahan ini. Sebagai partai yang lahir dan besar dalam demokrasi perwakilan versi lama, pilkada langsung bagi Golkar selalu terasa seperti baju pinjaman: dipakai karena zaman menuntut, dilepas ketika suasana berubah. Maka ketika wacana pemilihan oleh DPRD kembali muncul, Golkar menerimanya tanpa banyak drama ideologis.
Sementara PKB dan PKS tampak berjalan di lorong tengah, di satu sisi menyebut pentingnya aspirasi rakyat, di sisi lain membuka pintu kompromi dengan mekanisme elitis, selama bisa disebut maslahat dan sah secara hukum. Demokrasi pun diperlakukan seperti meja lipat, bisa dibuka ketika ramai, bisa dilipat ketika dianggap merepotkan.
Yang menarik, perubahan sikap ini jarang diakui sebagai pergeseran prinsip, melainkan dikemas sebagai penyesuaian teknis. Bahasa yang dipilih selalu rapi dan dingin, seolah demokrasi hanyalah urusan prosedur, bukan soal siapa yang memegang kunci kekuasaan.
Padahal, dalam politik, cara kita mengingat masa lalu sama pentingnya dengan keputusan hari ini. Demokrasi yang sehat tidak menuntut partai selalu benar, tetapi menuntut kejujuran: bahwa ketika arah berubah, yang bergeser bukan sekadar mekanisme, melainkan juga jarak antara rakyat dan mereka yang mengaku mewakilinya.
Narasi Efisiensi, Legitimitas yang Dipinjam dari Kemanusiaan
Pertama-tama, mari kita renungkan narasi yang sering dipakai untuk mendukung gagasan ini. Bahwa pilkada langsung “mahal”, “memakan biaya demokrasi yang besar”, dan oleh karena itu tidak layak dipertahankan.
Narasi semacam ini diproduksi bukan dalam ruang studi akademik semata, tetapi dalam arena persuasi politik. Tempat istilah-istilah seperti efisiensi, efektifitas, dan biaya tinggi dipreteli agar terlihat seolah berada di pihak kepentingan rakyat.
Tapi kita harus jujur pada diri sendiri, ketika elite politik berbicara soal biaya demokrasi yang besar. Apakah yang mereka maksud adalah operasional penyelenggaraan pemilu, atau biaya kampanye mereka sendiri, bukan biaya rakyat.
Biaya besar yang sering disebut itu barangkali adalah biaya yang dikeluarkan oleh kandidat, tim sukses, dan partai politik ketika bertarung di arena publik. Sedangkan biaya yang ditanggung masyarakat, dalam bentuk partisipasi, pengawasan, suara yang diabaikan, jarang disebut dalam hitungan mereka.
Ini adalah bentuk komunikasi politik yang manipulatif. Membingkai ulang demokrasi dan mendudukkan persoalannya sebagai beban fiskal. Padahal substansi sebenarnya adalah tentang hak untuk memilih. Narasi efisiensi ini secara retoris ingin kita menerima bahwa demokrasi bisa dirampingkan sampai sekadar urusan teknis.
Delegitimasi Ruang Publik
Pilkada langsung selama ini dibanggakan sebagai penerjemahan paling konkret dari kedaulatan rakyat, one man, one vote, one value. Meski literasi rakyat dalam memilih wakilnya harus terus ditingkatkan, tetapi sistem ini memungkinkan rakyat untuk tidak hanya memilih wakil mereka di parlemen, tetapi juga memilih pemimpin lokal yang mereka rasa paling mampu menjawab kebutuhan mereka.
Apa yang tidak disukai oleh narasi elit politik adalah ketidakpastian hasil ketika suara itu benar-benar ada di tangan rakyat, suara yang sulit diprediksi, suara yang semakin susah dan sulit bisa dibeli, suara yang sulit dikontrol oleh media mainstream.
Dengan mengalihkan pemilihan kepada DPRD, kita sebenarnya sedang mendelegitimasi ruang publik kita. Ruang di mana rakyat berbicara, berkumpul, berdebat, dan menentukan pilihan mereka sendiri.
Pergeseran semacam ini adalah bentuk halus dari pemusatan kuasa di tangan elit politik. Alih-alih memperkuat demokrasi, skema ini justru mereduksi partisipasi politik rakyat menjadi sebuah transaksi internal partai di meja legislatif. Terlebih, dalam hasil riset Indikator Politik Indonesia,per-akhir 2025 menunjukkan bahwa DPR dan Partai Politik menjadi dua lembaga yang termasuk paling tidak dipercayai publik.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak suara rakyat selama ini didengar melalui pesan politik yang dikurasi oleh partai dan elit politik, bukan melalui percakapan langsung. Rencana pilkada DPRD hanya memperkuat sistem yang di mana rakyat tidak lagi berbicara, tetapi hanya didengarkan dari pintu belakang parlemen.
Risiko Elitisasi Politik
Perubahan mekanisme pilkada ini juga berpotensi meningkatkan politik elitis, di mana politik bukan lagi tentang suara mayoritas di ruang publik, melainkan tentang negosiasi elit di ruang tertutup. Bahkan politisi yang mendukung ide ini pun kadang mengakuinya secara tersirat, bahwa pro-kontra akan muncul, tetapi perlu dikaji demi “kebaikan demokrasi”.
Biaya demokrasi mungkin dipandang tinggi oleh mereka yang bertugas mengumpulkan uang kampanye, tapi biaya demokrasi bagi rakyat adalah kepercayaan, partisipasi, dan peluang untuk terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin yang dinilai paling mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Jika kemudian yang dipilih adalah mekanisme yang menguatkan patronase politik, sistem dagang suara terstruktur, dan ketergantungan kepala daerah pada elite pusat, maka kita tidak berbicara tentang demokrasi. Kita berbicara tentang politisasi elite lokal yang diproduksi lewat kalkulasi yang jauh dari aspirasi rakyat.
Komunikasi Politik, Bahasa yang Menentukan Arah Demokrasi
Komunikasi politik bukan sekadar alat untuk menyampaikan gagasan. ia adalah arena konstruksi makna. Ketika politisi berbicara tentang pilkada melalui DPRD sebagai "solusi terhadap masalah biaya politik tinggi", mereka sebenarnya menasionalisasi narasi yang semula bersifat strategis substantif menjadi masalah yang tampak teknis.
Ini adalah strategi yang sudah lama dikenal di literatur komunikasi dengan istilah framing. Suatu praktik mengemas isu sedemikian rupa sehingga masyarakat yang menerima pesan akan menilai realitas berdasarkan frame yang disediakan. Bukan realitas faktualnya sendiri. Dalam situasi ini, wacana pilkada yang dilakukan oleh DPRD ditafsirkan sebagai alternatif yang lebih strategis, efektif, dan legal secara konstitusional. Meskipun ada kemungkinan besar untuk melemahkan kedaulatan rakyat.
Pertanyaan moralnya adalah apa yang lebih penting dalam demokrasi, mekanisme yang murah atau demokrasi yang substansial dan inklusif? Ketika kita mengamankan demokrasi dari elite partai dengan alasan pragmatis, kita sesungguhnya sedang menukar hak politik rakyat dengan kenyamanan sistem politik elite.
Antitesis Demokrasi, Ketika Keputusan Republik Dilihat dari Kursi Elite
Pilkada langsung bukanlah sekadar mekanisme pemilihan, tetapi simbol utama bahwa rakyat bukan hanya statistik, tetapi pemilik kedaulatan politik. Sistem itu membangun ruang publik yang inklusif, di mana suara rakyat direpresentasikan secara langsung, bukan melalui filter elite partai yang sering kali terpaksa korup, pragmatis, dan berorientasi pada kekuasaan.
Jika pilkada dialihkan pada DPRD, kita tidak hanya mengubah mekanisme, kita sedang memperbaharui narasi politik yang menjadikan elite partai sebagai pemegang otoritas tertinggi atas nasib demokrasi lokal. Ini adalah langkah yang bisa memperkuat struktur oligarki di Indonesia, elit yang memilih elit, dan rakyat yang dipilih hanya dalam statistik partisipasi semu.
Rakyat yang Dianggap Belum Dewasa
Ada nada paternalistik yang samar namun kuat dalam wacana ini. Seolah-olah rakyat dianggap belum cukup dewasa untuk memilih pemimpinnya sendiri. Terlalu mudah terpengaruh hoaks. Terlalu emosional. Terlalu gampang dibeli. Argumen ini terdengar ironis. Sebab jika rakyat dianggap tidak dewasa, pertanyaannya sederhana: siapa yang mendidik mereka selama ini?
Dalam komunikasi politik, partisipasi bukan hadiah untuk warga yang sudah pintar, tetapi proses pendidikan politik itu sendiri. Rakyat belajar berdemokrasi justru dengan terlibat, bukan dengan disingkirkan.
Menghapus pilkada karena rakyat dianggap belum siap sama saja seperti melarang anak belajar berenang karena takut tenggelam, lalu berharap suatu hari ia tiba-tiba bisa berenang sendiri. Rakyat dengan segala kekurangannya, tetap lebih layak dipercaya daripada elite yang terlalu yakin pada dirinya sendiri.
Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Partai?
Akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya mekanisme pilih-memilih, tetapi jiwa demokrasi itu sendiri. Apakah demokrasi kita adalah sistem yang membangun partisipasi rakyat secara luas? Atau apakah demokrasi itu hanyalah lambang legitimasi bagi elit elite yang duduk di parlemen?.
Masyarakat dari berbagai latar belakang perlu melihat lebih jauh daripada sekadar narasi efisiensi, pragmatisme, atau stabilitas pemerintahan. Mari kita tanyakan secara jujur “Apakah demokrasi yang sebenar-benarnya dimulai ketika rakyat berbicara di ruang publik? Atau ketika elite berbicara di ruang rapat tertutup?”
Demokrasi kita tak hanya soal suara yang dikumpulkan, tetapi soal suara yang dihormati, didengar, dan diputuskan oleh rakyat sendiri. Dan dalam demokrasi yang sehat, harga sebuah suara tidak pernah boleh hanya diukur dengan hal teknis biaya operasional, tapi lebih dari itu, ini tentang martabat warga negara yang memilihnya.
Mahbub Ubaedi, mahasiswa magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Peneliti di Lembaga Djarum Demokrasi
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang
2
Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun
3
Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur
4
Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah
5
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
6
Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa
Terkini
Lihat Semua